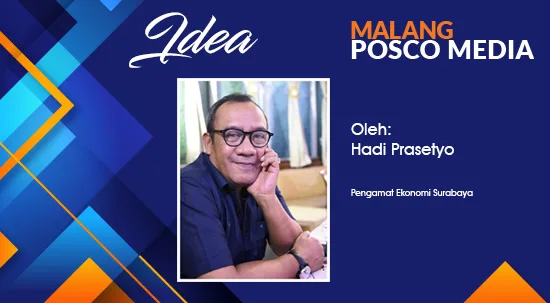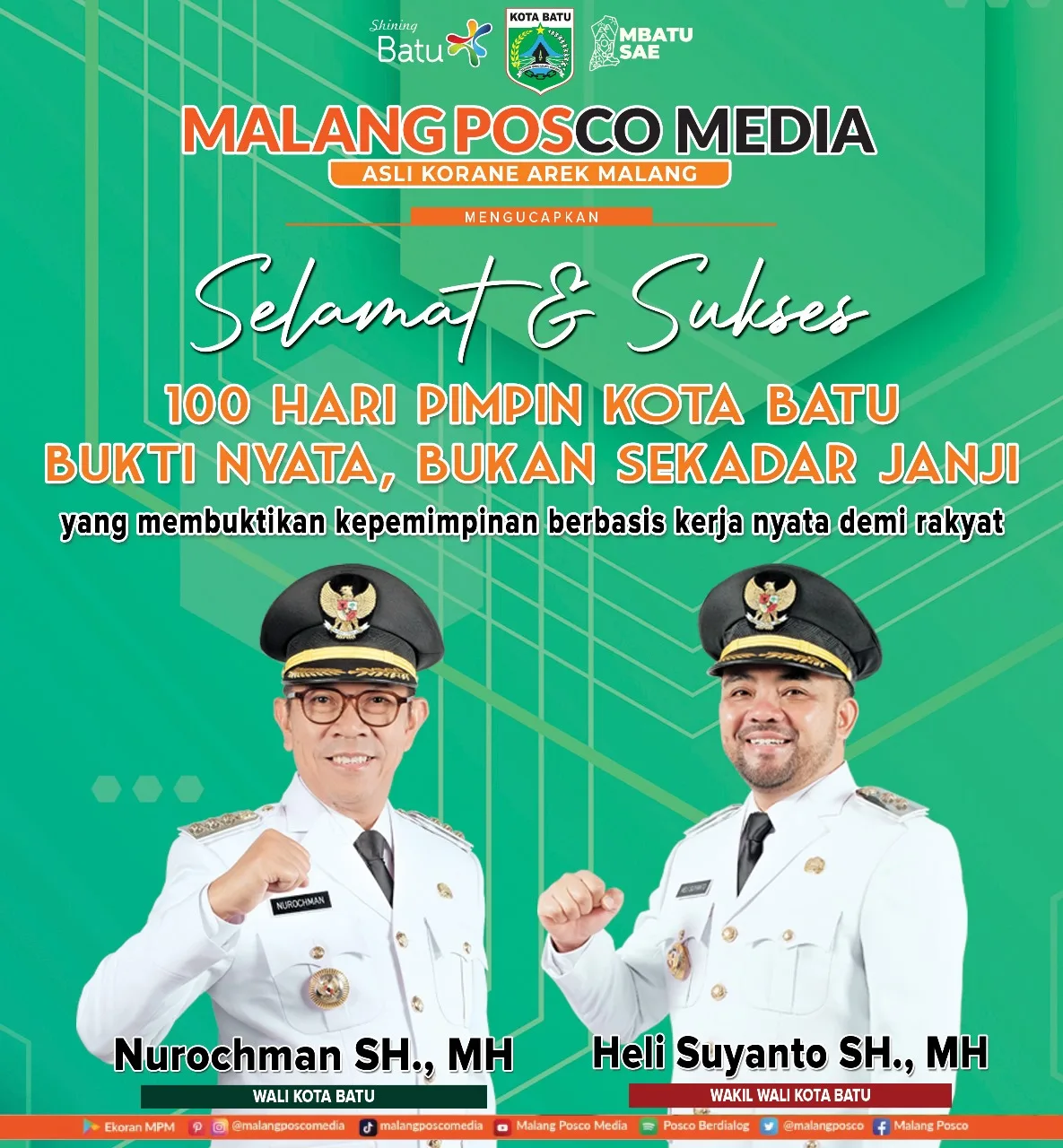Istilah transaksi adalah bagian dari konsep ekonomi, tetapi transaksional lebih dekat pada konsep politik praktis. Politik transaksional bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara berkembang, bahkan di demokrasi maju (misal lewat lobi korporasi di AS). Namun, di negara dengan pemerintahan yang transparan dan partisipasi publik kuat, praktik ini lebih mudah terdeteksi dan dikendalikan.
Perilaku transaksional dalam politik praktis adalah cermin dari “ketidak-seimbangan kekuasaan dan lemahnya institusi.” Meski bisa menjadi alat untuk mencapai kompromi pragmatis (ketika ada masalah) tetapi di dalamnya bisa saja terdapat hidden agenda sebagai upaya menutupi suatu misteri yang besar dan berisiko. Atau untuk menghentikan makin mengeruyaknya masalah menjadi bola salju sebagai boomerang goyahnya kekuasaan atau kemapanan politik kekuasaan.
Politik transaksional adalah praktik dimana hubungan politik dibangun melalui transaksi timbal balik (quid pro quo), seperti pertukaran dukungan (keamanan), jabatan, uang, atau akses ke sumber daya. Konsep ini berakar pada teori pertukaran sosial (Homans & Blau) yang banyak digunakan untuk menganalisis dinamika kekuasaan, patronase, dan korupsi dalam sistem politik, ibarat ‘pasar’ tempat aktor saling menukar “modal” (uang, pengaruh).
Belakangan ini banyak diberitakan secara luas kasus-kasus mega korupsi dengan jumlah besar (ratusan miliar hingga ratusan triliun) dialami oleh beberapa BUMN dan BUMD. Melihat besarnya nilai korupsi, masyarakat awam dengan logika sederhana (dan insting) menduga kuat tentu melibatkan para petinggi, entah langsung atau tidak langsung. Tetapi biarlah kasus korupsi diurus para penegak hukum.
Masyarakat lebih asyik mengamati dari luar, setelah terpaan isu dugaan korupsi besar, apa ada pergantian direksi dan komisaris. Jika ya siapa penggantinya, apa latar belakangnya, kira-kira lebih untuk perbaikan kinerja internal atau untuk mengatasi kasus-kasus yang belum terungkap? Atau keduanya? Atau transaksional?
Sebagai literasi, teori transaksional (pertukaran sosial) itu bukan ilmu eksak, karena mengandung variabel volatil, sering berubah misterius dan horor, dalam konteks politik kekuasaan yang labil. Teori ini bisa dikombinasikan dari sudut pandang post-truth yaitu istilah untuk menggambarkan situasi di mana fakta objektif dan kebenaran dianggap kurang relevan dibanding emosi, keyakinan pribadi, dan narasi sesuai dengan kepentingan politik.
Salah satu praksis fenomena post-truth, bisa dibaca dari buku “The Origins of Totalitarianism” (Hannah Arendt) yang menganalisis bagaimana rezim totaliter (tidak hanya kekuasaan nasional, tetapi bisa juga lokal) berusaha menutupi kebenaran objektif, menggantikannya dengan propaganda, dan sering menggunakan aparatus hukum untuk menekan perbedaan pendapat.
Maka dalam berbagai dugaan kasus korupsi yang besar di berbagai institusi negara, masyarakat yang cerdas akan mencoba menalar keterkaitannya dengan logika ‘if-then’ (jika-maka) meski tidak scientific. Masyarakat awam bukan kaum kampus, tetapi logika sederhana saja bisa membangun persepsi (curiga) dan opini yang terkait dengan ‘trust.’ Dan dalam suatu negara demokrasi, persepsi dan opini publik menjadi menakutkan.
Kembali pada fokus dimana banyak BUMN dan BUMD yang dewasa ini jadi bahan pembicaraan publik terkait mega korupsi, maka ketika suatu kasus mega sedang diselidiki (entah lanjut ke penyidikan atau berhenti begitu saja), publik akan terus mengawasi progresnya, sambil asyik berlogika ‘if-then’ dengan fakta perkembangan baru (misal tiba-tiba karena desakan publik ada pergantian direksi dan komisaris).
Pergantian jajaran petinggi bisnis oleh penguasa dianggap sudah dapat menjawab kekecewaan publik. Tapi publik kelas intelektual menengah itu pembelajar otodidak, didukung dengan berbagai ulasan media, atau juga dukungan aplikasi artificial intelligent (AI), bisa belajar mengkritisi, apakah suatu kebijakan sudah menyelesaikan masalah?
Dalam berbagai kasus korupsi, skandal yang tiba-tiba muncul mengagetkan sering hanya berupa ‘puncak gunung es’, sebagai akumulasi dari berbagai ‘fraud’ sebelumnya, mungkin bertahun-tahun, dalam paket-paket terpisah, tetapi melahirkan budaya organisasi yang manipulatif, walau berwajah apik, patuh regulasi karena dibungkus narasi apik dalam fenomena porst-truth.
Maka ketika ada pergantian petinggi suatu institusi bisnis, publik pun mengaitkan latar belakang para petinggi, sambil bertanya ada misteri apa lagi ya? Publik tidak bisa disalahkan karena ‘keingintahuan’ akan kebenaran merupakan ciri dari masyarakat yang makin cerdas dan kritis.
Ada pepatah “Semakin kompleks kebohongan, semakin rapuh pertahanannya.” Hal ini merujuk beberapa teori, misal: Streisand Effect dimana upaya menyensor atau menutupi informasi justru menarik perhatian publik terhadap hal yang ingin disembunyikan. Boomerang Effect dimana strategi meredam krisis justru memperburuknya karena dianggap manipulatif. Dan banyak teori lainnya.
Fenomena post-truth akan terus melahirkan kritik publik yang ingin kebenaran dan kejujuran. Lalu harus bagaimana? Opsi konsepsualnya hanya berkisar soal nasib beruntung atau apes. Nasib kehidupan sudah diurai dalam nasihat Prabu Joyoboyo: “Jaman edan, ora ngedan ora keduman. Luwih becik sing eling lan waspodo.” Nasihat bagus tentang DNA kehidupan.(*)