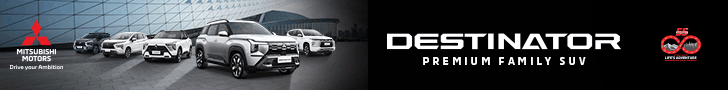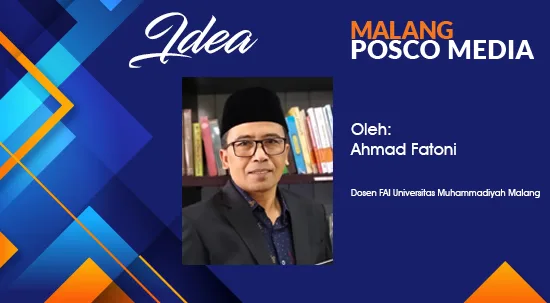Sejak runtuhnya rezim Orde Baru hingga pasca reformasi, kehidupan sosial politik di Indonesia mengalami guncangan yang begitu dahsyat. Demokrasi kemudian menjadi jargon yang kerap disuarakan, baik oleh elit politik, mahasiswa maupun masyarakat akar rumput. Pada satu sisi, ini merupakan perkembangan positif. Namun di sisi lain, euforia kebebasan justru melahirkan perilaku anarkis dan tindak kekerasan.
Harapan untuk membangun Indonesia Emas 2045 dengan sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis terdengar membumbung tinggi, begitu pula optimisme untuk keluar dari krisis ekonomi dan tekad menjadi negeri berdaya saing tinggi. Sayangnya, harapan itu perlahan pupus. Alih-alih membaik, bangsa ini justru semakin tersandra dalam krisis multidimensi; krisis kepercayaan, krisis politik, dan krisis kebangsaan. Petakanya, semua-mua krisis itu diperparah lagi oleh tingkah polah pemangku kekuasaan yang hedonis.
Pertanyaannya, apa yang mendorong masyarakat begitu mudah tersulut api amarah? Mengutip sosiolog Ignas Kleden dalam artikelnya Epistemologi Kekerasan di Indonesia (2000), ada tiga pendekatan untuk menganalisis kekerasan massa. Pertama, pendekatan politik yang melihat adanya aktor atau dalang di balik kerusuhan. Kedua, kesenjangan sosial sebagai dampak pembangunan. Ketiga, kekerasan massa sebagai refleksi dari sistem negara yang keras. Dari ketiganya, Kleden menilai analisis pertama terlalu dangkal, sementara yang kedua dan ketiga lebih bersifat psikologis serta struktural.
Solusi yang ditawarkan selama ini relatif seragam, yaitu membangun komunikasi, dialog, serta keberadaan lembaga kekuasaan untuk mencegah kerusuhan cenderung sporadis. Namun, masih menurut Kleden, pendekatan psikologi sosial justru jarang digunakan, padahal penting untuk memahami dinamika mental individu dalam kerumunan massa. Kala ratusan orang memiliki rasa frustrasi yang sama, lalu meluapkannya bersama, terjadilah ledakan kerusuhan yang sulit dikendalikan.
Faktor lain yang memperkuat sikap keras masyarakat adalah perilaku lembaga kekuasaan yang tidak adil, aparat yang sewenang-wenang, serta media sosial yang menayangkan berbagai tindak kekerasan secara vulgar.
Dalam setiap aksi unjuk rasa, kekerasan hadir dalam dua bentuk; fisik dan nonfisik. Aparat yang membubarkan demonstrasi dengan kekerasan bisa disamakan dengan demonstran yang melempari aparat dengan batu. Keduanya sama-sama melakukan tindak kekerasan. Bahkan, dalam konteks tertentu, kekerasan nonfisik dianggap wajar demi stabilitas sistem.
Namun kenyataannya, kekerasan di Indonesia—baik fisik maupun nonfisik—tidak bisa dilepaskan dari gaya negara yang keras. Pembangunan menciptakan norma-norma baru, tetapi juga mempersempit ruang penyaluran aspirasi politik.
Banyaknya larangan membuat masyarakat kehilangan saluran ekspresi, hingga kemarahan akhirnya diarahkan pada simbol-simbol kekuasaan. Seperti gedung pemerintah, pusat ekonomi, hingga rumah-rumah pejabat yang diduga mengkhianati amanat rakyat.
Sejumlah pakar menilai, salah satu akar persoalan adalah absennya lembaga pemerintah yang tak mampu membangun kompromi secara dialogis. Masyarakat tidak pernah dilatih untuk mengelola konflik. Setiap konflik selalu dianggap terkendali dengan mencari kambing hitam atau dalang kerusuhan, tanpa menyentuh akar persoalan.
Lantas, apa yang kita inginkan bersama? Tentu bukan menjadi masyarakat kekerasan (violence society). Kita berharap kecenderungan itu bisa ditekan, bahkan idealnya dihapus. Budaya menghindari konflik tidak bisa terus dipertahankan. Dalam dunia global yang kian sempit, kita harus belajar mengelola konflik dengan pendekatan lebih luas, baik secara budaya maupun psikologis.
Celakanya, aneka kanal media sosial yang semakin canggih justru gagal berfungsi sebagai sarana komunikasi publik. Informasi diperdagangkan, bukan dijadikan bahan dialog. Alih-alih agama, yang senyatanya menjadi penyejuk, kerap diajarkan dengan cara emosional, sehingga justru memperkeruh suasana.
Kasus Kerusuhan Massa
Gelombang unjuk rasa di berbagai daerah Indonesia belakangan ini menunjukkan kecenderungan mengkhawatirkan. Aksi yang dimulai secara damai justru kerap berakhir dengan kericuhan massal, bentrokan, hingga jatuhnya korban.
Pertama, kericuhan besar terjadi di Jakarta pada 25 Agustus 2025 saat ribuan massa menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI. Kedua, aksi di Temanggung pada 1 September 2025 juga berakhir ricuh. Ketiga, aksi di Makassar bertajuk Indonesia Gelap pada 24 Februari 2025 berujung pada bentrokan keras. Keempat, kericuhan di Bandung dan Tasikmalaya menambah daftar panjang kerusuhan massa. Kelima, jumlah peserta aksi yang ditangkap di Jakarta sepanjang akhir Agustus 2025 mencerminkan skala masalah.
Polda Metro Jaya memeriksa lebih dari 1.200 orang, sementara secara nasional Polri mengamankan 3.195 orang dan menetapkan 55 tersangka. Data ini menegaskan bahwa unjuk rasa di Indonesia kini rawan berubah menjadi ajang kekerasan massal.
Kerusuhan dan tindak kekerasan tidak cukup dipahami lewat pendekatan psikologi sosial semata. Analisis senyatanya melibatkan dimensi politik, struktural, dan budaya. Sebab, kekerasan di Indonesia kian kompleks, rumit, dan saling terkait. Agar unjuk rasa kembali menjadi wadah aspirasi yang sehat, diperlukan upaya perbaikan dari dua sisi, baik pemerintah dan aparat yang lebih mengedepankan dialog, serta masyarakat yang menjaga aksi tetap damai dan konstruktif.(*)