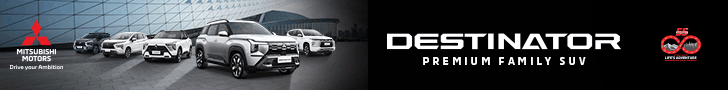Dalam panggung raksasa bernama Indonesia, setiap warga negara seolah dipaksa memainkan peran yang telah dituliskan dalam naskah tak terlihat. Ada yang didapuk menjadi penonton setia yang bertepuk tangan, ada yang sekadar figuran di latar belakang, dan tentu saja, segelintir elite yang merangkap sebagai sutradara sekaligus pemain utama.
Namun, jangan salah, ini bukanlah sebuah opera agung yang berakhir saat tirai diturunkan. Di panggung ini, setiap dialog, setiap adegan, dan setiap properti yang digunakan mempertaruhkan sesuatu yang jauh lebih fundamental: nyawa dan nasib warga biasa yang kerap tak punya pilihan selain mengikuti alur cerita yang telah dipatenkan.
Mesin kekuasaan negeri ini adalah ahli tata cahaya yang ulung; ia menyalakan lampu sorot paling terang saat mengumbar janji, lalu meredupkannya hingga nyaris padam saat tiba waktunya menagih pertanggungjawaban. Di depan kamera, para politisi melafalkan mantra sakti “kedaulatan rakyat” dengan fasihnya. Namun di belakang layar, jejaring mafia sibuk memperdagangkan nasib orang-orang kecil dalam senyap.
Tiga kata kunci terus-menerus didengungkan sebagai pembenaran: “stabilitas,” “ketertiban,” dan “kedaulatan.” Padahal, terjemahan sesungguhnya dari “stabilitas” adalah pembungkaman kritik, “ketertiban” adalah perapian jejak kejahatan elite, dan “kedaulatan” yang seharusnya menjadi hak prerogatif rakyat justru menjadi dalih untuk menukar hutan dengan konsesi tambang dan menggusur kampung adat demi megaproyek oligarki.
Medan perang hari ini tidak lagi riuh oleh suara ledakan, melainkan senyap dalam lembaran regulasi, klausul konsesi, dan orkestrasi para pendengung bayaran. Pasal-pasal karet dalam Undang-Undang siap diayunkan laksana cambuk bagi siapapun yang berani melawan, sementara tender-tender proyek strategis “sudah terkunci” bahkan sebelum diumumkan.
Bantuan sosial dibagikan laksana konfeti dalam sebuah parade meriah saat kamera menyala, namun lenyap tak berbekas begitu lampu panggung dimatikan. Publik digiring untuk bertepuk tangan atas kemurahan hati yang ironisnya didanai dari kantong mereka sendiri, dikembalikan dalam bentuk paket sembako yang tanggal distribusinya disesuaikan dengan kalender politik.
Dampak dari dramaturgi ini meresap hingga ke akar rumput. Di desa, peta tanah adat dilipat-lipat sesuka hati, dan warga dihadapkan pada ilusi pilihan: “ganti untung atau ribut?” Di kota, buruh terperangkap dalam rezim kontrak yang kian cair, di mana gaji dibekukan, jaminan sosial menjadi jargon kosong, dan serikat pekerja dikebiri atas nama “iklim pro-investasi.”
Sementara di pesisir, nelayan diminta minggir untuk memberi jalan bagi kapal-kapal raksasa tak beridentitas yang bebas mengeruk ruang hidup mereka. Negara memang hadir, tetapi bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai event organizer yang sibuk menyewakan panggung kepada penawar tertinggi. Kehadirannya justru terasa melalui ketidakhadirannya bagi mereka yang paling membutuhkan.
Untuk menjaga pertunjukan ini tetap berjalan, citra dikelola secara presisi. Fakta dipotong pendek-pendek, konteks dibuang jauh-jauh, dan para pendengung bernyanyi dalam satu koor serempak: “Jangan baper, ini demi masa depan!” Siapapun yang berani mengkritik akan segera dicap sebagai pesanan lawan.
Di negara sandiwara ini, kebenaran tidak lagi dicari, melainkan di-casting. Siapa yang paling laku dijual, itulah “kebenaran” yang berlaku pekan ini. Kekerasan pun kini punya penata adegan sendiri; ia tidak selalu hadir dalam bentuk pukulan, tapi sering kali dalam penundaan sidang, penghilangan barang bukti, atau pembalikan beban pembuktian yang membuat korban tampak seperti pelaku.
Perang paling sunyi justru terjadi di arena memori kolektif. Buku-buku sekolah disterilkan dari bab-bab sejarah yang dianggap “mengganggu persatuan,” tragedi kemanusiaan disusutkan menjadi tanggal merah tanpa makna, dan korban diubah menjadi angka statistik yang dingin.
Media lebih tertarik menyorot seremoni gunting pita para pejabat ketimbang gunting buldoser yang memotong peta kampung dan merobek masa depan warganya. Ketika sejarah dikurasi oleh mereka yang berkepentingan, publik hanya mewarisi sebuah album foto keluarga yang seluruh keterangannya telah dihapus.
Lalu, apa yang tersisa selain sinisme? Jalan keluarnya bukanlah sekadar menukar aktor di atas panggung, sebab panggungnya itu sendiri yang sudah lapuk. Mengganti rezim hanya akan melahirkan lingkaran setan kekuasaan baru. Kita butuh langkah-langkah yang tidak dramatis namun fundamental: membangun koperasi yang benar-benar milik anggota, serikat kerja yang mandiri dari partai politik, dan mengaudit kas RT secara terbuka.
Politik sejati bukanlah di bilik suara lima tahun sekali; politik adalah saat kita menentukan harga gabah, memperjuangkan jarak sekolah yang lebih dekat, atau memastikan puskesmas punya stok obat yang cukup. Ketika ruang-ruang kecil ini direbut kembali, sandiwara besar itu akan mulai kehilangan penonton.
Maka, hadiri rapat lingkungan meski lelah. Tanyakan kuitansi pengeluaran RW walau dicap “rese.” Dokumentasikan kekerasan dengan aman. Negara sandiwara ini hidup dari dua hal: penonton yang patuh dan ingatan yang pendek. Maka, hanya ada dua kebiasaan yang perlu kita latih untuk melawannya: membantah dan mengingat.
Bantah setiap narasi yang menukar keadilan dengan kecepatan proyek. Ingat setiap nama yang dihilangkan dan setiap janji yang diucapkan sambil tersenyum. Kelak, saat tirai ditutup dan para aktor meminta tepuk tangan, kita bisa serempak berkata: “Cukup. Panggung ini kami bongkar. Bukan untuk membangun yang lebih mewah, tapi untuk menanam kebun di bekasnya—agar hidup tidak lagi jadi lakon, melainkan jadi hak.”(*)