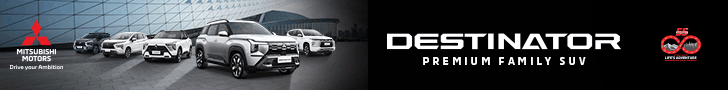Di tengah derasnya gelombang popularitas, kabar tentang Sahara dan Yai Mim menjelma menjadi salah satu tontonan sosial paling ramai di jagat maya. Ceritanya terdengar absurd namun memikat. Seorang tokoh karismatik berseteru dengan seorang perempuan muda pebisnis rental mobil.
Perpaduan antara spiritualitas dan bisnis itu menjelma drama kolosal yang nyaris sempurna untuk dikonsumsi publik digital, terutama bagi jamaah whatsappiyah dan tiktokiyah. Namun di balik absurditas dan kehebohannya, kisah tersebut menyuguhkan banyak hal tentang karakter masyarakat yang haus sensasi.
Sosiolog klasik asal Jerman Ferdinand Tönnies membedakan antara Gemeinschaft (paguyuban) dan Gesellschaft (patembayan) untuk mengklasifikasikan dua tipe masyarakat berdasarkan ikatan antaranggota. Dalam masyarakat paguyuban, relasi antarindividu didasari nilai-nilai moral. Sementara dalam masyarakat patembayan, hubungan menjadi impersonal, pragmatis, dan serba transaksional.
Kasus Sahara–Yai Mim memperlihatkan bagaimana media sosial mempercepat pergeseran tipe sebuah masyarakat. Di ruang digital, publik bukan lagi sekadar penonton, namun juga partisipan dalam menciptakan narasi. Komentar, unggahan ulang, dan meme menjadi bentuk “kontrak sosial baru” yang lahir dari rasa ingin tahu dan keinginan untuk terlibat.
Yai Mim yang semula mungkin hanya tokoh agama di wilayah tertentu, tiba-tiba menjadi ikon nasional — bukan oleh sebab kapasitas spiritualnya, tetapi karena drama yang menyertainya. Inilah contoh paling gamblang bagaimana otoritas tradisional tergeser oleh otoritas viral yang menjadikan kekuatan simbolik tidak lagi bersumber dari ilmu, melainkan dari interaksi dan algoritma.
Politik Tubuh dan Krisis Moral Digital
Sahara, sosok perempuan yang tak kalah menarik, disorot bukan karena prestasi, melainkan karena posisinya yang berseteru dengan Yai Mim. Dalam banyak komentar warganet, tubuhnya dijadikan komoditas; dihakimi, dipuji, dihina, bahkan dijadikan bahan konten.
Fenomena tersebut memperlihatkan apa yang disebut Michel Foucault sebagai politik tubuh — bagaimana tubuh menjadi medan kuasa. Sahara kehilangan otonomi atas dirinya begitu kisahnya viral. Ia menjadi “milik publik” dan direduksi menjadi bahan konsumsi moral sekaligus hiburan. Ironisnya, dalam masyarakat digital, popularitas justru sering lahir dari keterpurukan. Semakin seseorang disorot karena drama, semakin besar peluangnya menjadi selebriti algoritma.
Sahara bukan hanya korban konflik personal, tetapi juga korban sistem media yang mengubah tragedi menjadi trending topic. Di satu sisi, dunia maya menawarkan ruang ekspresi tanpa batas. Namun di sisi lain, ia menjadi penjara transparansi. Foucault menyebutnya sebagai sistem pengawasan tanpa dinding, bahwa setiap orang bisa mengintip dan diintip tanpa henti. Dalam situasi semacam ini, batas antara penghakiman dan hiburan menjadi kabur. Publik merasa berhak menilai, bahkan atas hal-hal yang bersifat paling privat.
Di sisi lain, Yai Mim menggambarkan krisis otoritas moral di tengah masyarakat yang haus validasi digital. Tokoh agama yang dulu dihormati karena otoritas keilmuan dan keteladanannya kini terjebak dalam arena komentar dan live streaming.
Yai Mim barangkali dulunya mengandalkan karisma spiritual, namun media sosial memaksa otoritas itu bergeser menjadi karisma digital yang diukur dari jumlah followers, likes, dan tayangan live. Ketika konflik muncul, legitimasi itu goyah sebab penilaian publik lebih cepat daripada proses klarifikasi.
Fenomena Sahara–Yai Mim senyatanya tak lahir dalam ruang hampa. Ia merupakan bagian dari tatanan baru yang menjadikan manusia sebagai komoditas. Kasus Sahara–Yai Mim adalah gambaran nyata tentang kinerja kapitalisme yang mampu mengubah konflik sosial menjadi konten digital.
Hakim Bernama Netizen
Kasus Sahara–Yai Mim menandai lahirnya krisis kepercayaan publik terhadap institusi moral. Masyarakat tak lagi menunggu penjelasan tokoh, melainkan membentuk pengadilan moral sendiri. Di titik ini, moralitas berubah menjadi tontonan dan berubah menjadi algoritma yang harus dioptimalkan agar tetap relevan di linimasa.
Tak ada yang lebih cepat membentuk opini publik selain timeline. Dalam hitungan jam, netizen sudah menulis ribuan komentar, membuat parodi, dan bahkan menggelar sidang moral tanpa pengadilan. Drama Sahara dan Yai Mim bisa dibaca sebagai bentuk baru sanksi sosial digital. Di satu sisi, ia menunjukkan partisipasi publik yang tinggi. Namun di sisi lain, ia juga membuktikan kegagalan sistem sosial dalam menyediakan ruang refleksi.
Di dunia maya, tidak ada waktu untuk menunggu fakta dan yang terpenting adalah menjadi yang pertama berkomentar. Penikmat tontonan Sahara dan Yai Mim hanyalah cermin dari masyarakat yang sedang mengalami kejenuhan budaya (cultural fatigue), semacam kesumpekan hidup dalam menghadapi berbagai persoalan, lalu mencari pelarian lewat hiburan sosial.
Dengan menertawakan Sahara–Yai Mim, kita sesungguhnya sedang menertawakan diri sendiri sebagai masyarakat yang kehilangan batas antara keseriusan dan lelucon. Lebih jauh, drama Sahara–Yai Mim menunjukkan bahwa kita hidup dalam era banalitas moral. Kini nilai-nilai etis tak lagi dicari, melainkan dipilih sesuai selera algoritma.
Akhirnya, kisah Sahara dan Yai Mim mungkin akan menghilang dari linimasa seperti isu-isu viral lainnya. Namun maknanya akan tetap tersisa sebagai potret zaman yang mempertukarkan nilai-nilai dan spiritualitas dengan viralitas. Sebagaimana petuah kaum sosiolog modern, kita sesungguhnya sedang menulis skenario sendiri yang menghamba kepada viralitas.
Sementara kita sendiri lupa bahwa yang benar-benar berkonflik bukan hanya Sahara–Yai Mim, melainkan batin kita yang haus pengakuan. Di sinilah tragedi terbesar manusia digital: ia berteriak tentang moral di ruang publik, tetapi kehilangan kedamaian di ruang sunyi hati nurani.(*)