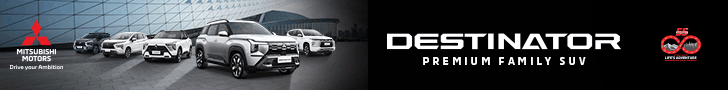Program Xpose Uncensored di stasiun televisi Trans7 dinilai menyinggung Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Gelombang seruan boikot terhadap Trans7 ramai disuarakan. Gelombang kemarahan publik terhadap sebuah acara televisi membuka kembali perdebatan tentang relasi antara media dan masyarakat. Aksi boikot tak hanya tindakan menolak menonton, namun bahasa simbolik untuk mengatakan bahwa cermin media itu sudah buram dan harus dibersihkan.
Video tayangan Xpose Uncensored produksi Production House (PH) rekanan Trans7 itu beredar luas. Banyak pihak yang menilai tayangan tersebut dapat menyinggung dan merendahkan para kiai dari Pondok Pesantren Lirboyo. Komunitas santri dan alumni pesantren menganggap tayangan tersebut bukan sekadar kesalahan biasa, namun bentuk penghinaan terhadap kehormatan ulama dan tradisi Islam pesantren.
Trans7 sudah menyampaian permohonan maaf, mengakui kesalahan, menarik tayangan, dan berjanji melakukan evaluasi. Namun, permohonan maaf itu tak serta merta memadamkan api kekecewaan. Di ruang budaya pesantren, kiai bukan sekadar figur publik. Mereka adalah pusat kehormatan moral, penjaga tradisi, dan representasi adab. Menghilangkan martabat kiai dalam program televisi berarti menyentuh saraf terdalam dari identitas kolektif komunitas santri.
Cermin yang Memburam
Media massa sering dianalogikan sebagai cermin masyarakat. Ia merefleksikan realitas sosial, mengangkat cerita, dan menyusun narasi. Persoalannya, cermin itu tak selalu bersih. Terkadang ia memantulkan sesuatu secara menyimpang. Demi mengejar rating dan viralitas, tak jarang media televisi tergoda untuk memilih sensasi daripada etika. Maka wajar bila cermin itu tak hanya memantulkan masyarakat, tetapi juga membentuk citra palsu.
Dalam kasus Trans7, persoalannya bukan hanya tentang kreativitas tayangan. Ini tentang krisis sensitivitas budaya yang lebih luas. Trans7 mencoba bermain-main dengan simbol agama dan tradisi pesantren, tanpa memahami dimensi spiritual, kultural, dan sosialnya. Ketika media memperlakukan sosok kiai sebagai bahan hiburan, publik merasa martabat kolektif mereka direduksi menjadi komoditas tontonan.
Melalui kekuatan media sosial saat ini publik mampu mengorganisasi kemarahan. Mereka tak hanya memprotes, tetapi juga mengawal narasi. Di sinilah boikot menjadi alat negosiasi kekuasaan. Publik tentu tak punya kontrol atas studio, kamera, atau ruang redaksi Trans7. Tapi mereka memiliki satu senjata paling berbahaya bagi media yakni memutus kepercayaan pada media. Dan kepercayaan itu adalah modal termahal bagi pengelolaan media.
Dalam kajian komunikasi, hal ini disebut audience resistance yakni perlawanan khalayak media terhadap hegemoni media. Publik tak lagi hanya mau menjadi konsumen media yang pasif. Mereka menuntut peran sebagai pengadil moral terhadap isi siaran. Jika media melukai nilai sosial, publik tak segan menarik legitimasi mereka. Maka aksi boikot tak hanya sebagai ekspresi kemarahan, melainkan menjadi strategi tekanan sosial.
Kasus serupa pernah terjadi sebelumnya. Program “Pesbukers” di ANTV pernah mengalami boikot karena dianggap melecehkan profesi guru, ulama, dan bahkan menampilkan lawakan merendahkan fisik dan agama. Acara “Lapor Pak!” yang juga tayang di Trans7 juga pernah diprotes karena candaan tentang pesantren. Program “Indonesian Idol” juga pernah menuai kemarahan publik ketika salah satu jurinya dianggap bermain-main dengan bacaan doa. Sejumlah acara dan stasiun televisi lain juga pernah mengalami boikot.
Boikot: Bersihkan Cermin
Aksi boikot sebenarnya bisa jadi alat sensor massal. Dalam sejumlah kasus, praktik media sering ceroboh dan tak hati-hati. Ada kalanya media sedang menantang tabu guna membuka wawasan publik, tetapi lebih sekadar memancing reaksi demi sensasi. Di tengah demokrasi digital, media tak bisa lagi bekerja dengan paradigma lama yakni hanya dengan pertimbangan yang penting ramai.
Boikot media semestinya tak dibaca sebagai upaya memecahkan cermin media, tetapi sebagai upaya membersihkan cermin itu. Sesungguhnya publik tak sedang anti media. Mereka hanya ingin media menjadi cermin yang bijak dan bukan distorsi yang melukai. Ada wilayah sensitif yang tak bisa dengan mudah divisualisasikan dan dinarasikan sembarangan. Di sinilah media perlu menjunjung adab dan budaya.
Dalam tradisi pesantren, adab adalah pondasi pengetahuan. Hal ini yang perlu dipelajari oleh industri media bahwa membangun narasi tak hanya membutuhkan kreativitas, tetapi juga rasa hormat. Ketika Trans7 tersandung masalah saat ini, maka tak cukup hanya dengan meminta maaf. Mereka perlu mengembangkan literasi kultural, memahami batas-batas simbolik masyarakat. Jika tidak, boikot akan menjadi siklus yang terus berulang.
Dari sejumlah kasus yang berujung aksi boikot menunjukkan satu benang merah bahwa publik ingin mengingatkan pada media bahwa kebebasan berekspresi tak boleh meninggalkan etika. Media boleh kreatif, tapi tak boleh abai. Media sebagai cermin bisa menjadi buram karena laku media yang lebih mengejar tujuan menghibur sementara mencederai martabat, agama, suku, etnis, atau kelompok tertentu.
Aksi boikot terhadap Trans7 bukan sekadar perlawanan emosional. Ini adalah panggilan agar media kembali bercermin. Bukan untuk melihat rating, tetapi melihat tanggung jawabnya. Cermin media itu mungkin berdebu, penuh bias, sensasi, dan lupa adab. Namun cermin tak perlu dipecahkan. Ia hanya perlu dibersihkan. Dan boikot dipilih bukan tindakan destruktif, melainkan alarm moral yang mengingatkan bahwa kebebasan media tanpa empati hanya akan berujung pada resistensi publik.(*)