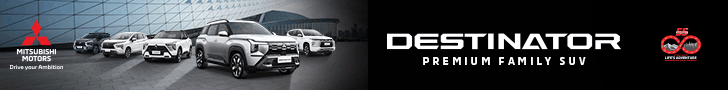Beberapa waktu lalu viral lagu dangdut berjudul “Santri Pekok.” Lagu yang diciptakan oleh Arif Citenk ini penulis lihat di YouTube dinyanyikan oleh Happy Asmara, Defarina Indra, Niken Salindri, dan sejumlah penyanyi lain. Lagu ini juga banyak di cover sejumlah penyanyi yang videonya bertebaran di YouTube dan TikTok. “Santri Pekok” lagu yang cukup jenaka, berkisah tentang seorang preman yang ingin mempersunting seorang santriwati lulusan pondok.
Coba kita simak penggalan syair lagunya. “Tak rewangi ngempet ora ngerokok/Macak sopan ben koyo kang pondok// Eh, eh ladalah suwengku lali nyoplok/Jare bapake aku koyok santri pekok//.” Lagu ini menggambarkan perjuangan seorang pria menjadi pribadi yang lebih baik demi mendapatkan gadis pujaannya, seorang santriwati lulusan pesantren. Namun, sang pria tak mampu berperilaku layaknya santri pondok, hingga disebut santri pekok.
Lagu ini tentu hanya sebagai hiburan semata. Syairnya mudah dicerna dan mengena dengan kehidupan masyarakat. Irama musiknya dangdut yang gampang diterima banyak kalangan penikmat musik tanah air. Kata “pekok” yang ditempelkan di belakang kata “santri” dalam lagu ini hanya untuk mengilustrasikan bahwa menjadi santri itu tak main-main. Santri itu menjunjung adab dengan baik.
Secara harfiah kata “pekok” berasal dari bahasa Jawa yang bisa berarti bodoh, dungu, atau tolol. Kata “pekok” secara umum sesungguhnya tak tepat kalau disematkan untuk seorang santri. Santri adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu di sebuah pondok pesantren. Mereka belajar dari para ustadz dan kiai. Mereka adalah manusia-manusia terdidik seperti halnya siswa atau mahasiswa di lembaga-lembaga pendidikan formal non pesantren.
Framing Santri
Beberapa pekan ini bermunculan konten di media sosial (medsos) yang melakukan pembingkaian (framing) tentang sosok santri dan pesantren. Berawal dari peristiwa ambruknya bangunan di pondok pesantren Al Khoziny di Buduran Sidoarjo. Dengan cepat berita peristiwa itu menyebar viral lewat beragam platform media digital. Kesempatan ini tak disia-siakan oleh para pembuat konten (creator content) yang membuat aneka konten tentang pesantren dan santri.
Namun sayang, tak semua konten yang muncul dibuat oleh mereka yang benar-benar mengerti tentang kehidupan pesantren. Tak sedikit kreator konten yang membuat tayangan tentang pesantren dan santri menurut framing mereka sendiri tanpa memahami budaya pesantren. Tak sedikit pembuat konten tersebut seperti hanya memburu algoritma digital agar konten mereka mendapat kunjungan dan monetisasi yang besar.
Salah satu framing media yang jadi polemik adalah acara Xpose Uncencored Trans7. Tayangan Trans7 tersebut telah menyinggung pesantren, kiai, dan santri. Framing acara tersebut melenceng. Pembuat acara tak memahami dengan benar dunia pesantren. Dalam kajian komunikasi, media punya kekuatan untuk membentuk realitas. Ketika media menampilkan citra pesantren dan santri secara keliru maka publik akan percaya bahwa itulah realitasnya. Inilah yang disebut stereotyping effect.
Media acapkali membingkai pesantren dan santri secara keliru. Dalam sejumlah sinetron, komedi, dan konten medsos, santri kerap digambarkan sebagai sosok lugu, lucu, dan “ndeso”, berbicara gagap, berpakaian kumal, dan hidup dalam keterbelakangan. Pesantren divisualisasikan sebagai tempat yang kuno, tertutup, dan seperti tak bersentuhan dengan dunia modern.
Framing semacam ini bisa membentuk persepsi keliru tentang pesantren dan santri. Framing bahwa santri hanyalah pelaku ritual keagamaan yang hanya nurut apa kata kiai tanpa kemampuan berpikir kritis tidaklah tepat. Sejatinya justru kaum santri adalah motor utama kebangkitan intelektual dan nasionalisme. Mereka belajar banyak hal, tak hanya tentang ilmu agama.
Santri Era Digital
Tak sedikit pihak yang keliru memahami dan merepresentasikan budaya pesantren (cultural misrepresentation). Narasi tentang santri sedang direbut di ruang publik. Jika para santri diam, maka orang lainlah yang akan menulis cerita tentang santri. Para santri perlu terus aktif menulis, bernarasi, berdiskusi, memproduksi konten, dan tampil sebagai intelektual publik. Para santri perlu terus menegaskan bahwa santri bukan simbol keterbelakangan.
Tantangan santri hari ini bukan lagi kolonialisme atau feodalisme, tetapi arus digital yang tak terbendung. Dunia maya memproduksi informasi, hoaks, dan hiburan dalam kecepatan tinggi. Di sinilah santri dituntut memainkan peran baru yakni sebagai penjaga akal sehat publik. Santri yang sejati bukan hanya menghafal kitab, tetapi juga mampu menafsirkan realitas digital. Mereka harus cakap bermedia, mampu membaca algoritma, memahami propaganda, dan melawan disinformasi.
Media hiburan sering kali tergoda menampilkan gambaran yang “menjual.” Semua dikemas dalam logika hiburan, tetapi melupakan tanggung jawab kultural. Ironisnya, framing semacam itu justru dikonsumsi oleh generasi muda yang minim pengetahuan tentang dunia pesantren. Kita sedang hidup di era visual, di mana persepsi lebih kuat daripada fakta. Ketika pesantren direduksi menjadi sekadar latar ironi, maka citra santri pun ikut terkikis. Sejarah membuktikan bahwa santri adalah kelompok sosial yang cerdas, progresif, dan visioner. Dari pesantren lahir ulama, intelektual, pemimpin bangsa, dan inovator. Itu bukti santri bukan pekok. Santri adalah simbol resilience (ketangguhan) mempertahankan budaya di tengah gempuran arus globalisasi. Santri tak anti modernitas, hanya menolak kehilangan jati diri. Selamat Hari Santri.(*)