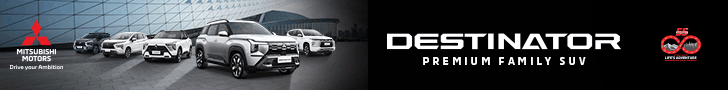Di era digital saat ini, tak sedikit orang terkena sindrom bebek (duck syndrome). Kalau kita lihat bebek di kolam terlihat tenang dan mengambang. Sebenarnya di dalam kolam sang bebek berjuang keras menggerakkan kakinya agar mampu bertahan di permukaan air. Itulah gambaran sindrom bebek yang menjangkiti masyarakat di mana mereka ingin terlihat sempurna melalui pencitraan diri dengan berjuang mati-matian demi mendapatkan kesan sempurna itu.
Tak jarang orang justru tak menjadi dirinya sendiri. Mereka selalu melihat orang lain sebagai ukuran dan berusaha tampil melebihi orang lain. Sindrom bebek ini menjadikan masyarakat tak bisa hidup tenang dan santai. Mereka selalu mengejar penilaian orang lain agar dilihat sebagai orang yang lebih segalanya dibandingkan dengan yang lain. Para pengidap sindrom bebek ini hidupnya penuh dengan pencitraan yang melelahkan.
Kemunculan sindrom bebek ini tak lepas dari dampak kehidupan di era digital saat ini. Melalui beragam platform media sosial (medsos) banyak orang berjuang mati-matian guna menampilkan diri sebagai sosok yang selalu terlihat wah. Segala cara ditempuh guna mendapatkan pengakuan dan validasi dari orang lain. Para pengidap sindrom bebek ini hidupnya jadi tersiksa karena ia berusaha sangat keras hanya demi pencitraan diri.
Sindrom Bebek
Sindrom bebek (duck syndrome) bukan bermakna orang yang ikut-ikutan seperti halnya hewan bebek yang punya kebiasaan mengikuti kemanapun hewan di depannya pergi. Sindrom bebek bermakna seperti halnya bebek ketika berenang di air terlihat tenang namun sesungguhnya kakinya berjuang sangat keras agar tak tenggelam. Banyak masyarakat yang harus berjuang sangat keras walaupun seperti terlihat tenang.
Duck syndrome dapat diartikan sebagai kondisi ketika seseorang berusaha menutupi kesulitan dan kewalahan dirinya, hanya untuk menunjukkan citra diri sempurna di hadapan orang lain. Penyakit sindrom bebek ini memang bukan penyakit fisik. Penyakit ini banyak menyerang kelompok masyarakat kelas menengah. Di balik kemapanan yang mereka citrakan, banyak masyarakat kelas menengah yang harus jungkir balik membayar cicilan dan tagihan.
Istilah duck syndrome awalnya dikenalkan oleh Universitas Stanford Amerika Serikat untuk menggambarkan para mahasiswanya yang tampak tak kesulitan mencapai nilai terbaik meski kenyataannya mereka harus jungkir balik. Konsekuensi terkena sindrom bebek ini menjadikan hidup jadi ngoyo dan kurang bersyukur karena selalu melihat kelebihan orang lain dan membandingkannya dengan diri sendiri.
Dalam masyarakat digital, terutama era medsos, sindrom bebek semakin marak terjadi. Orang cenderung membagikan konten di medsos hanya sisi terbaik dari kehidupan mereka, menciptakan ilusi bahwa mereka menjalani hidup yang sempurna. Hal ini dapat memicu perasaan tak cukup baik pada orang lain yang melihatnya, meskipun mereka juga mungkin sedang mengalami situasi serupa.
Budaya Performatif Medsos
Medsos adalah ekosistem tempat sindrom bebek tumbuh subur. Aneka platform medsos seperti Facebook (Meta), Twitter (X), Instagram (IG), TikTok, YouTube, dan WhatsApp (WA) didesain untuk menampilkan versi terbaik dari diri penggunanya, bukan versi yang utuh dan jujur. Di medsos banyak orang suka memosting prestasi, pencapaian, momen bahagia, foto yang telah diedit atau dipilih dari banyak opsi, dan narasi yang terkurasi.
Dunia digital menjadi ruang yang penuh ilusi yang memperkuat duck syndrome. Banyak orang seperti tampak tenang dan bahagia, padahal banyak yang sedang berenang mati-matian di bawah. Duck syndrome selalu mendorong orang melakukan pencitraan, sementara pencitraan butuh validasi, dan validasi memperkuat pencitraan. Situasi ini semakin menjadikan individu semakin jauh dari keaslian dirinya.
Dalam budaya digital saat ini, keberhasilan sosial diukur dari seberapa kita dapat likes, views, dan engagement. Maka banyak orang yang harus menyembunyikan kelemahan, takut terlihat gagal, dan berusaha keras menyesuaikan diri agar tetap pantas tampil di linimasa. Hal ini menciptakan tekanan psikologis dan emosional yang terus-menerus demi menjaga citra yang lebih penting dari menjaga diri.
Di medsos juga muncul second account alias akun alter, finsta, atau akun pelarian yang banyak digunakan untuk mengekspresikan emosi asli, tempat curhat, meluapkan kegelisahan, atau menjadi diri sendiri. Ia adalah ruang perlawanan terhadap budaya selalu harus terlihat sempurna dan bukti bahwa masyarakat digital sadar akan beban pencitraan. Second account bisa untuk melihat perilaku masyarakat yang memperlihatkan “kaki bebek yang mengayuh keras.”
Budaya performatif adalah situasi ketika orang hanya merasa perlu tampil, bukanmenjadi. Budaya ini membawa banyak orang menampilkan versi ideal dari dirinya dan bukan versi jujur yang sesuai kenyataan. Di medsos algoritma digital hanya memberi reward pada konten menarik, bukan konten jujur. Medsos membuat penggunanya terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Seolah-olah hidup harus luar biasa agar layak dilihat.
Budaya performatif medsos adalah akar sosiokultural dari fenomena duck syndrome dan pencarian validasi digital. Budaya ini merupakan bentuk tekanan sosial digital yang halus tapi sistemik. Ia menjauhkan kita dari kejujuran, keutuhan, dan kemanusiaan. Agar tak terjangkiti sindrom bebek maka kita perlu memperbanyak konten yang mampu menciptakan ruang digital yang lebih otentik, jujur, dan manusiawi.(*)