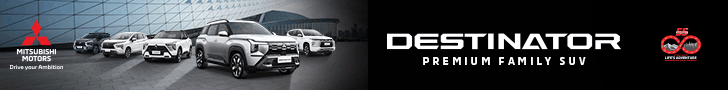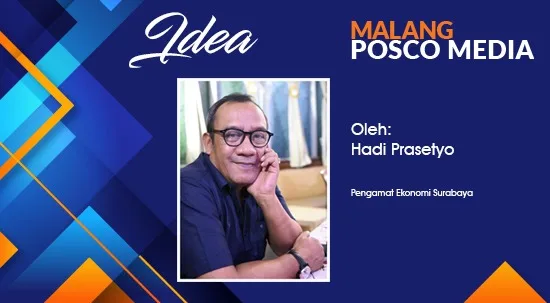Dalam suatu link youtube, ekonom senior Prof. Ferry Latuhinin menilai kebijakan yang ditawarkan Purbaya berpotensi menyalahi prinsip dasar hukum ekonomi. Menurutnya, langkah-langkah yang tidak sejalan dengan mekanisme pasar bisa menimbulkan distorsi dan berisiko bagi stabilitas ekonomi nasional.
Tulisan ini mencoba mengulas kebijakan Purbaya dalam konteks “Shadow Economy” dan “Ketidakpastian Usaha.” Mungkin ini bisa memberikan sedikit gambaran mengapa Purbaya begitu pemberani. Kemumetan yang dirasakan ekonom sangatlah wajar karena teori ekonomi konvensional dibangun atas asumsi.
Pertama, Aktor rasional, dimana pelaku ekonomi bertindak untuk memaksimalkan keuntungan. Kedua, Situasi informasi diasumsikan tersebar merata (atau setidaknya, asimetri informasi bisa dimodelkan). Ketiga, Mekanisme pasar berjalan relatif normal dimana harga adalah sinyal utama yang mengalokasikan sumber daya. Keempat, Peran negara terbatas dan jelas, dimana regulator menetapkan aturan, pasar yang menjalankannya.
Ketika seorang pembuat kebijakan seperti Purbaya mengambil langkah yang tampak “menyalahi hukum ekonomi” dalam kerangka di atas, ia sebenarnya mungkin sedang berurusan dengan variabel yang tidak (atau kurang) tercakup dalam model-model teoritis tersebut, yaitu “shadow economy.”
Critical analyis dan kreativitas yang dijalaninya di bidang engineering semasa S1 sebelum mengambil pendidikan ekonomi, mungkin mendorong pemikiran ‘kreatifnya’ untuk menelusuri peran dan pengaruh ‘hidden economy’ dalam kaitannya dengan konsep GDP, APBN dan fiskal.
Maklum Purbaya pernah menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tentu mempunyai data-data statistik terkait potensi finansial masyarakat dan berbagai profil pemiliknya di cross section analyis dengan berbagai variabel data lain, misal korporat, data portfolio dan lain sebagainya.
Hidden economy yang juga ‘Shadow Economy” mungkin itulah yang disasar Purbaya, untuk mencari terobosan ekonomi dan fiskal yang ‘landai’ dan kurang menggerakkan sektor ekonomi riil.
Shadow economy atau ekonomi bayangan ini memiliki karakteristik khusus. Pertama, mencakup nominal besar dan menghasilkan uang. Aktivitasnya nyata, uangnya nyata, tetapi tidak tercatat dalam statistik resmi PDB/GDP. Ini mencakup transaksi tunai tanpa kuitansi, suap, rent-seeking, hingga aliran dana untuk kepentingan politik.
Kedua, tidak berkorelasi dengan ekonomi riil atau portfolio teoritis. Inilah sumber “kemumetan.” Ekonomi riil (produksi, konsumsi, investasi produktif) dan pasar keuangan formal punya teori korelasinya (seperti antara suku bunga dan investasi). Sementara shadow economy bergerak dengan logikanya sendiri, seringkali berbasis pada akses kekuasaan dan informasi orang dalam.
Ketiga, umumnya pelaku shadow economy besar dekat dengan otoritas kekuasaan politik. Ini adalah kunci utamanya. Shadow economy sering kali bukan sekadar ‘UMKM’ yang tidak berizin, tetapi lebih kepada ekonomi yang hidup karena dan untuk kekuasaan. Ia menjadi sumber dana untuk membiayai mesin politik, memelihara loyalitas, dan membangun hegemoni.
“Optimisme” Purbaya memang sebuah pertaruhan yang berisiko tinggi. Optimisme Purbaya mungkin berasal dari keyakinannya untuk: Pertama, “memutus mata rantai.” Kebijakannya bisa jadi ditujukan untuk memutus hubungan simbiosis antara kekuasaan dengan shadow economy. Jika berhasil, fondasi ekonomi bisa menjadi lebih sehat dan kompetitif.
Kedua, memaksa transisi dengan “mengganggu” aliran dana shadow economy. Dia mungkin berharap uang-uang itu akan beralih ke sektor formal yang lebih produktif dan terdokumentasi. Ketiga, menyasar akar ketimpangan karena banyak ketimpangan dan inefisiensi bersumber dari praktik shadow economy yang dikuasai segelintir orang dekat kekuasaan.
Namun, risiko terbesarnya justru kedekatan shadow economy dengan kekuasaan. Kebijakan yang menyentuh kepentingan elite politik dan pelaku shadow economy yang sangat berkuasa akan menghadapi perlawanan yang sangat kuat, baik secara terang-terangan maupun melalui “perang politik.”
Dampaknya bagi pelaku usaha adalah “ketidakpastian ekonomi” sangat terasa di lapangan. Bagi pelaku usaha (kecil-menengah yang legitimate), kebijakan ini menciptakan ketidakpastian karena aturan berubah tidak terduga. Langkah-langkah yang “tidak lazim” sulit diprediksi dengan model bisnis biasa.
Di samping itu kekhawatiran timbulnya gejolak politik-ekonomi yang dipersepsi masyarakat sebagai “perang politik” antara Purbaya dan pihak yang dirugikan menciptakan turbulensi. Pelaku usaha terjebak di tengah-tengah, kesulitan membaca arah kebijakan jangka menengah-panjang.
Dalam perkreditan, ada kekhawatiran kredit macet dan risiko sistemik. Jika kebijakan ini menyebabkan goncangan pada pelaku besar yang terlibat shadow economy, bisa memicu kredit macet dan gejolak di sektor perbankan yang akhirnya berdampak ke semua usaha. Kebijakan Purbaya ini tampaknya adalah sebuah intervensi struktural yang sangat ambisius, bukan sekadar intervensi siklikal (seperti menaikkan/ menurunkan suku bunga).
Purbaya berusaha mengubah “rules of the game” yang telah berjalan lama. Dari sisi teori langkah ini bisa dilihat sebagai upaya institutional economics yaitu mengubah institusi (aturan formal dan informal) untuk mengubah perilaku ekonomi. Namun, transisinya selalu menyakitkan dan penuh ketidakpastian.
Dari sisi realitas politik, keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan politik yang sangat kuat dari pucuk pimpinan (Presiden). Jika tidak, Purbaya bisa jatuh sebagai “pahlawan yang kalah sebelum perang usai.”
Sementara itu dari sisi pelaku usaha, ketidakpastian adalah musuh utama investasi. Tanpa komunikasi yang jelas dan peta jalan yang transparan, kebijakan ini justru bisa menekan investasi dari pelaku usaha “yang bersih” yang ketakutan dengan gejolak yang ditimbulkannya.
Jadi, “kemumetan” para ekonom klasik sangat bisa dipahami. Ini adalah pertarungan antara teori ekonomi murni dengan ekonomi politik yang kompleks dan berdarah-darah. Optimisme Purbaya adalah sebuah lompatan imajinasi bahwa shadow economy bisa ditaklukkan.
Namun, sejarah sering membuktikan bahwa “naga” itu lebih sering ditaklukkan untuk dijinakkan dan dikendarai, bukan untuk dibunuh. Dalam guyonan warung kopi, masyarakat ‘bisa bantu’ Purbaya dengan ‘mengitik-itik’ “ketiak naga” supaya geli dan ketawa terpingkal-pingkal, agar gumpalan ‘harta karun’ terlepas dari cengkeramannya dengan gembira, karena tidak ada naga yang ikhlas apalagi murah hati.(*)