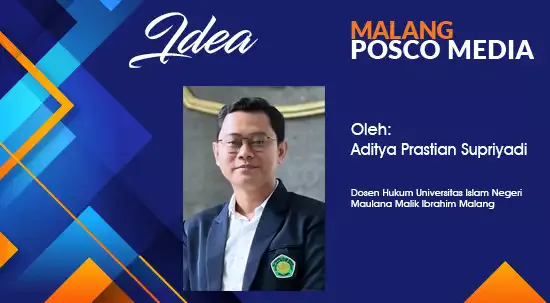Di tengah peringatan kemerdekaan, kita kerap berbicara tentang makna “merdeka” dalam berbagai dimensi. Ironisnya, dalam kemerdekaan ekosistem musik Indonesia terasa semu. Gonjang-ganjing aturan royalti terakhir ini memunculkan dilema paradoksal. Di satu sisi ingin melindungi hak ekonomi pencipta. Namun di sisi lain menimbulkan rasa takut di kalangan pengguna. Fenomena ini menandakan perlu menimbang ulang apakah kebijakan royalti musik saat ini menjamin keadilan ekonomi? atau justru menjadi belenggu kreativitas?
Royalti musik diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa setiap pemanfaatan ciptaan di luar penggunaan pribadi wajib memperoleh izin pencipta atau pemegang hak cipta, dan biasanya disertai pembayaran royalti.
Untuk pelaksanaannya, hadir Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang berwenang mengelola, memungut, dan mendistribusikan royalti. Bahkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2021 mengatur tata cara penarikan dan pembagian royalti secara lebih detail dengan skema tarif baku yang wajib dipatuhi pengguna.
Di atas kertas, desainnya masuk akal. Tetapi praktiknya sering kali tampil dalam wajah “represif.” Restoran akhirnya memilih menonaktifkan musik. Bukan karena musiknya buruk. Tetapi karena takut menghadapi sanksi. Bahkan untuk menghindari royalti, musik dialihfungsikan ke suara alam demi mencegah risiko hukum.
Inilah ironi di negeri yang Merdeka. Kemerdekaan berkarya terasa semu ketika regulasi yang seharusnya melindungi justru mengekang kreativitas.
Paradoks Royalti
Dalam perspektif hukum ekonomi, aturan royalti seharusnya dirancang bukan hanya untuk melindungi hak eksklusif pencipta. Tetapi juga untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan karya. Prinsip dasar hukum ekonomi mengajarkan regulasi harus menyeimbangkan antara protection dan promotion. Perlindungan tanpa promosi akan melahirkan stagnasi. Promosi tanpa perlindungan akan menggerus insentif berkarya. Sayangnya, regulasi royalti kita saat ini terlalu berat sebelah pada aspek proteksi dan minim inovasi dalam aspek promosi penggunaan karya.
Pada konteks kemerdekaan, persoalan ini menjadi semakin relevan. Kemerdekaan berekspresi dan berkarya dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 yang mengakui hak setiap warga negara untuk mengembangkan diri dan memperoleh serta menyebarkan informasi melalui media apa pun.
Di sisi lain, Pasal 28H ayat (4) memberikan jaminan atas perlindungan hak milik pribadi, termasuk hak cipta. Dengan demikian, ada dua hak konstitusional yang harus dipertemukan. Hak pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dan hak masyarakat untuk mengakses serta memanfaatkan karya.
Masalahnya, ketika royalti dipersepsikan sebagai ancaman, akses publik terhadap karya menjadi terbatas. Persoalan ini bukan hanya merugikan pengguna. Tetapi juga merugikan pencipta sendiri akibat potensi ekonomi karya mereka tidak tereksploitasi secara optimal.
Dalam teori Law and Economics, ini adalah bentuk deadweight loss dalam pasar kreatif. Karya yang seharusnya menghasilkan nilai tambah ekonomi justru “menganggur” akibat tingginya hambatan transaksi.
Paradigma Baru
Momentum kemerdekaan seharusnya menjadi refleksi. “Kemerdekaan” dalam konteks ekonomi kreatif harus dimaknai karya dapat mengalir bebas, digunakan secara luas, dan pada saat yang sama tetap memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta. Di sinilah perlu adanya perombakan paradigma dalam pengelolaan royalti.
Pertama, kita memerlukan mekanisme tarif royalti yang adaptif dan proporsional. UUHC memang memberikan kewenangan LMKN menetapkan tarif. Namun prinsip keadilan ekonomi menghendaki agar tarif disesuaikan dengan skala dan tujuan penggunaan.
Misalnya, pemutaran musik di kafe berkapasitas 20 kursi semestinya dibebani tarif tetap yang ringan daripada konser berskala stadion yang wajar dikenakan persentase tertentu dari total penjualan tiket.
Kedua, kita butuh platform digital terpadu yang transparan dan akuntabel. Pasal 87 UUHC sebenarnya mengamanatkan pengelolaan data karya dan pengguna secara transparan. Namun praktiknya masih banyak keluhan terkait distribusi royalti yang lambat dan tidak merata. Dengan teknologi blockchain atau sistem pelacakan digital, setiap penggunaan karya bisa tercatat otomatis, meminimalisir sengketa, dan membangun kepercayaan publik terhadap LMKN.
Ketiga, penegakan berbasis edukatif. Misalnya, jadikan lisensi sebagai syarat perizinan keramaian yang diproses satu pintu. Sanksi peringatan, denda ringan, denda penuh diberlakukan sebelum langkah pidana. Dan mediasi cepat diterapkan untuk sengketa tarif.
Pola ini menutup ruang “menakut-nakuti” sekaligus mempercepat kepatuhan. Apalagi arah kebijakan terbaru royalti bertujuan mempertegas kewajiban pembayaran royalti pada layanan publik komersial. Penajaman prosedur yang fair di hilir akan membuat penegasan ini terasa sebagai kepastian, bukan ancaman.
Dengan reformasi semacam ini, semangat kemerdekaan pada ekosistem musik dapat terwujud. Pencipta tetap “merdeka” dalam mendapatkan hak ekonominya. Sementara pengguna “merdeka” untuk mengakses dan memanfaatkan karya tanpa rasa takut berlebihan. Kemerdekaan di sini bukan berarti bebas dari kewajiban. Tetapi bebas dari ketidakpastian dan intimidasi hukum.
Akhirnya, kemerdekaan sejati dalam industri kreatif hanya dapat tercapai jika hukum hadir sebagai fasilitator. Bukan intimidator. Regulasi royalti yang bijak tidak membuat karya menganggur dan tidak membuat pencipta kehilangan haknya. Sebaliknya, ia menjadi penghubung yang harmonis antara kreativitas dan manfaat ekonomi.
Karena di era ini, kemerdekaan tidak hanya ditentukan oleh bendera yang berkibar. Tetapi juga oleh musik yang bisa mengalun bebas, dinikmati semua orang, sambil tetap menghargai jerih payah penciptanya.(*)