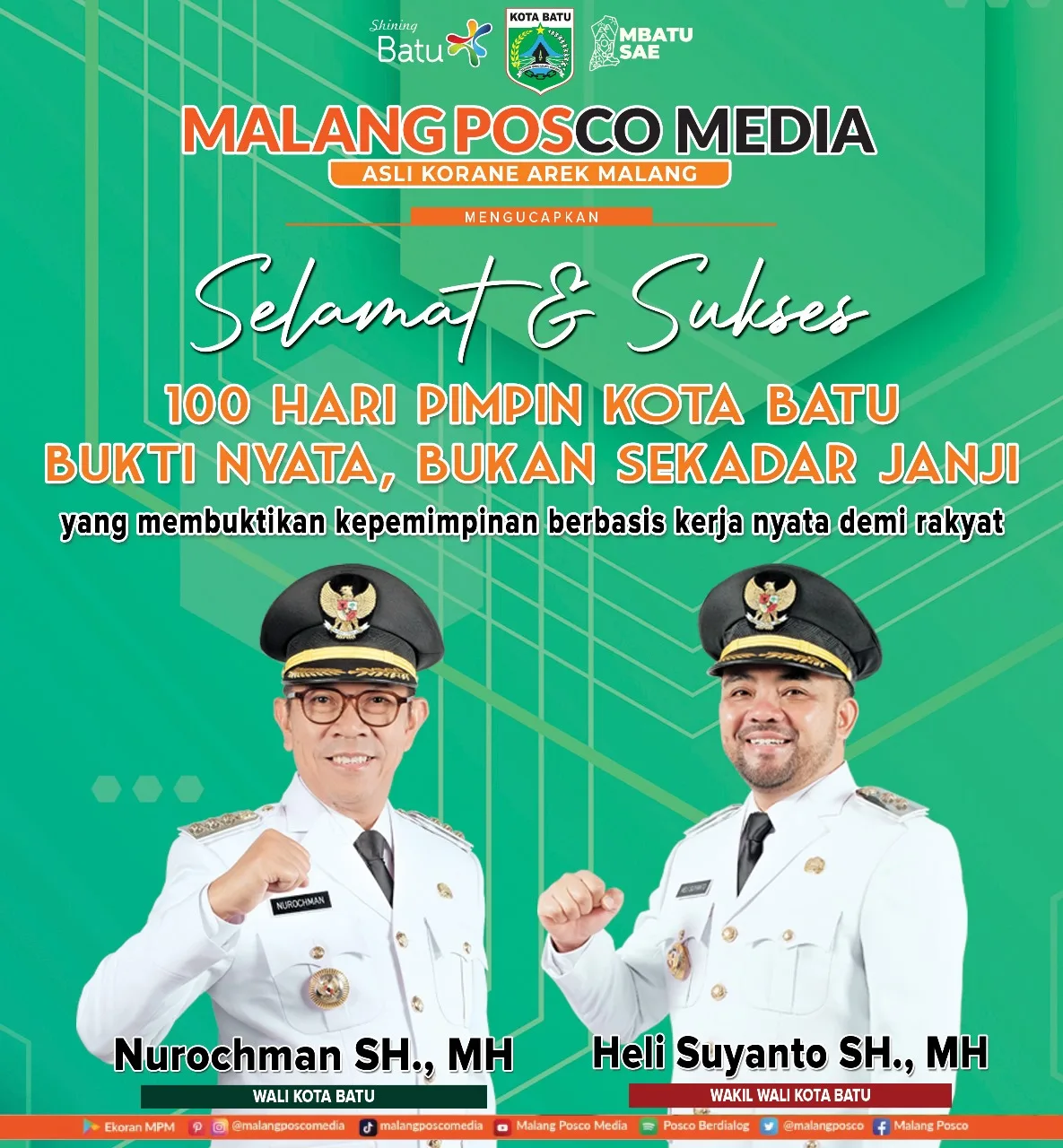Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) marak terjadi. PHK juga menimpa industri media massa tanah air. Sejumlah stasiun televisi, media cetak, dan elektronik harus memangkas jumlah wartawannya. PHK (layoff) di sektor media pers tak boleh terus terjadi. Tanpa kehadiran media massa arus utama (mainstream media) bisa memperburuk demokrasi karena pers adalah pilar demokrasi yang penting.
Beberapa pekan lalu muncul video seorang presenter acara olah raga di Kompas TV yang berpamitan sambil terisak harus mengakhiri program yang sudah belasan tahun mengudara. Berdasarkan sejumlah sumber, selain Kompas TV, iNews, MNC group, CNN, TVOne, Viva, Emtek Group, Global TV, TVRI, RRI, ANTV, Net TV, dan beberapa media lain, melakukan perampingan dengan memangkas puluhan hingga ratusan jurnalisnya.
Beberapa permasalahan memicu terjadinya musim gugur industri media. Perkembangan teknologi berbasis kecerdasan imitasi (artificial intelligence) diduga telah menggeser sejumlah peran jurnalis. Masalah lain terkait model bisnis, kegagalan melakukan konvergensi media dan mediamorphosis. Kue iklan pun terus menipis menjadikan industri media harus melakukan efisiensi yang berujung pada pengurangan jumlah pekerja.
Hal serius lain yang harus dihadapi industri media adalah kuasa beragam platform media sosial (medsos) yang mampu memalingkan khalayak, menjadikan medsos sebagai sumber informasi yang utama. Pergeseran pola konsumsi media ke medsos juga semakin dikuatkan dengan hadirnya banyak pemengaruh (influncer) yang dengan leluasa membuat konten informasi yang banyak diakses masyarakat.
Situasi ini menjadikan tak sedikit iklan yang sebelumnya menjadi nyawa bagi industri media pers, kini berpindah ke beragam platform medsos dan para influencer. Banyak instansi pemerintah dan swasta yang menghabiskan belanja iklannya ke medsos dan bayar para pemengaruh. Kuasa medsos sebagai media nirjurnalisme (bukan jurnalistik) punya andil pada terjadinya layoff di sejumlah industri media.
Kuasa Nirjurnalisme
Lahirnya internet yang melahirkan aneka teknologi turunannya, termasuk medsos, telah mengubah cara banyak orang mengakses informasi. Kebutuhan informasi tak lagi hanya dicari lewat media massa konvensional, namun banyak yang beralih ke medsos. Fenomena ini semakin kuat didukung oleh tingkat aksesibilitas masyarakat pada medsos dan media digital yang semakin tinggi.
Kuasa platform digital global seperti Google, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, telah menjadikan media nirjurnalisme tersebut menjadi media utama bagi kebanyakan orang. Situasi ini berimbas pada berpalingnya pemasang iklan yang beralih ke platform digital global tersebut. Kuasa raja digital (digital lord) yang cenderung monopolistik dan menguasai bisnis informasi mulai hulu hingga hilir menjadikan ekosistem media tak sehat.
Media nirjurnalisme mengklaim sebagai media informasi, tapi tak menjalankan prinsip dan praktik jurnalisme yang sahih. Media ini umumnya mengabaikan nilai-nilai dasar jurnalisme seperti verifikasi, independensi, keberimbangan, dan akurasi. Media nirjurnalisme merusak ekosistem informasi publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat pada media massa, memperparah polarisasi sosial, dan mempersulit publik dalam membedakan informasi yang kredibel dan manipulatif.
Media nirjurnalisme tumbuh subur bukan karena keunggulan informasinya, melainkan karena kuasanya dalam menarik perhatian, menggugah emosi, dan mengisi kekosongan kepercayaan pada media konvensional. Melawan kuasa media nirjurnalisme tak cukup hanya dengan menertibkan medianya, tetapi juga membangun literasi media publik dan memperkuat jurnalisme yang berkualitas.
‘Mediamorphosis’
Sejumlah alternatif pemecahan masalah (solusi) perlu dicari agar industri media tetap terjaga keberlangsungannya. Medianya tetap eksis dan para pekerjanya bisa semakin sejahtera. Atmosfir industri media harus sehat agar masyarakat memperoleh haknya mendapatkan berita dan informasi yang baik dan benar, terhindar dari beragam kabar bohong (hoax) dan berita palsu (fake news).
Tawaran konsep mediamorphosis yang digagas oleh Roger Fidler (1997) bisa jadi solusi. Fidler menjelaskan bagaimana media berkembang dan berubah seiring waktu, terutama ketika media baru muncul dan berinteraksi dengan media yang sudah ada. Menurut Fidler, mediamorphosis adalah proses transformasi media komunikasi yang terjadi sebagai respons terhadap tekanan teknologi, budaya, politik, dan ekonomi.
Konsep mediamorphosis sangat relevan untuk memahami perubahan media massa, ruang redaksi, dan masa depan industri media. Mediamorphosis memberi penekanan bahwa media massa lama tak akan hilang, tapi perlu berubah. Inovasi yang patut dilakukan bukan dengan mengganti, tapi menyerap, memodifikasi, dan menjaga eksistensi. Dalam kaitan ini, media yang mampu bertahan bukan yang paling tua atau paling baru, tapi yang paling adaptif.
Media massa harus mampu melawan kuasa media nirjurnalisme. Industri media tak boleh kolaps, jatuh, roboh, atau bahkan mati. Jika media massa mati, tak hanya pelaku industri media dan para pekerjanya saja yang rugi, masyarakat juga dirugikan karena bisa tak mendapatkan informasi yang kredibel dan berkualitas. Tanpa media pers bisa terjadi krisis informasi berkualitas. Melalui hasil kerja jurnalis mampu melahirkan produk jurnalisme yang terstandar, tak seperti aneka produk informasi yang disajikan medsos.
Kalau mau demokrasi tetap tegak maka media pers tak boleh mati. Media pers justru perlu semakin diperkuat. Perlu dukungan semua pihak agar ekosistem industri media massa tetap sehat. Para pelaku media juga perlu terus berinovasi menyikapi perubahan termasuk merespon perubahan yang dipicu oleh lahirnya teknologi baru.(*)