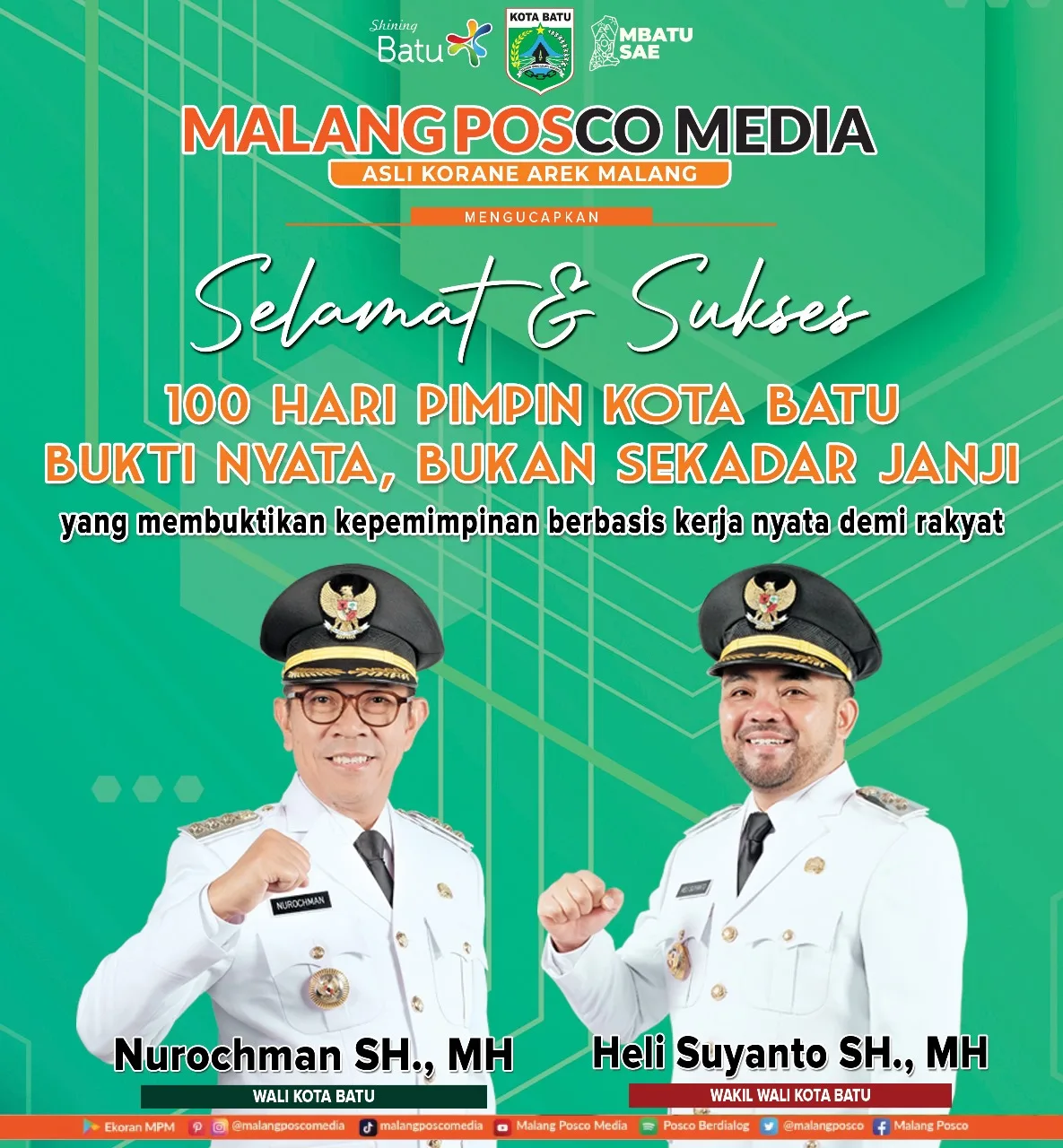LIBURAN kali ini begitu istimewa. Akhir libur berjumpa hari bersejarah, yakni hari Pendidikan. Liburan berakhir adalah awal yang harus dijalani kembali untuk menuju kenyataan yang sesungguhnya. Kegiatan kembali berjalan normal dan produktif. Baik itu di perkantoran, industri, perniagaan. Termasuk dunia pendidikan.
Liburan kali ini berada pada persilangan momentum menarik yang bisa dipergunakan untuk membangun titian kenyataan dan kesadaran untuk menjemput pilihan dan masa depan. Bukan karena kesengajaan, liburan kali ini bersamaan dan beriringan dengan 3 (tiga) peristiwa besar di negeri ini. Yakni, pertama,bulan suci Ramadan dan lebaran. Kedua, hari buruh (may day). Ketiga, hari Pendidikan.
Peristiwa itu tidak berdiri tunggal dan saling terpisah, saling berkaitan. Ringkasnya, tiga momentum itu menyisipkan dan bicara mengenai masa depan dan kesadaran. Khususnya, hari Pendidikan. Pidato Pembelaan Mohammad Hatta –akrab dengan Bung Hatta—sebagai salah seorang proklamator dalam pengadilan Den Haag Belanda, 9 Maret 1928 lampau patut untuk disimak kembali.
Pidato Pembelaan Bung Hatta dikenal dengan tajuk “Indonesia Merdeka” (Indonesie Vrij) yang dibaca selama 3,5 jam mengupas habis tentang praktik eksploitasi dan sisi lain dari kolonialisme. Sebelum mengakhiri pidatonya, Bung Hatta menyuarakan dengan penuh yakin dan optimis dengan mengatakan bahwa ‘’Saya rela dipenjara asalkan bersama buku karena dengan buku saya bisa bebas.’’
Pernyataan Bung Hatta lalu ditutup dengan kalimat menarik, yakni kami percaya di masa yang akan datang Bangsa Indonesia dan kami percaya kekuatan kami ada pada jiwa kami. Pidato Indonesia Merdeka itulah yang membebaskan Bung Hatta dari jeratan hukum subversive di pengadilan Den Haag Belanda.
Tidak lama dari keputusan hukum Pengadilan Den Haag, dalam tahun yang sama. Kongres Pemuda II digelar. Bagi Bangsa Indonesia, bulan Oktober adalah lahir dan bangkitnya kesadaran nasionalisme, yang dipelopori oleh 8 tokoh anak-anak muda yang akhirnya mendorong terjadinya Kongres II Pemuda, tahun 1928 silam.
Kongres itu pula yang melahirkan “sihir” kebangsaan, yang selalu dikenang dan dijadikan cermin bagi bangsa Indonesia, yaitu: Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda meninggalkan benih nasionalisme yang tak lapuk oleh waktu dan gerak modernisme. Napas nasionalisme Sumpah Pemuda tersebut hingga kini masih kuat aura dan gaungnya.
Sumpah Pemuda tidak sekadar nasionalisme. Namun sudah menjelma menjadi ikrar dalam jiwa jiwa anak anak muda untuk menyelamatkan negeri ini dari keterpurukan dan tekanan eksternal. Ikrar itu secara tegas dan tidak ada penawaran sedikitpun. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia.
Satu dari tiga ikrar tersebut, yakni menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia sebagai pengikat nasionalisme.
Napas nasionalisme yang tertinggal, layak dijadikan energi baru dalam mengawali semangat hari pendidikan kali ini. Tidak hanya para pelaku pendidikan, mulai dari guru, siswa, karyawan, mahasiswa dan dosen. Untuk menyelamatkan roh pendidikan yang sesungguhnya. Terlebih lagi, kampanye merdeka belajar yang hingar bingar di awal rintisan kebijakan namun mulai luntur semangatnya.
Menjadi siswa, mahasiswa, guru dan dosen dengan mengesampingkan sejarah panjang yang dilalui sebagai seorang siswa, mahasiswa, guru dan dosen yang pernah disandang sesungguhnya hanya sebatas membunyikan ikrar dan tanpa jiwa yang utuh.
Karena dalam perjalanan waktu, waktu dirinya hanya dihabiskan masalah administrasi, prosedur untuk siswa, mahasiswa, guru dan dosen yang baik secara sistem. Tak ada waktu yang tersisa untuk melihat masalah kemanusiaan yang terjadi di sekitarnya. Meski, napas pendidikan adalah masalah kemanusiaan.
Padahal Ikrar sebagai siswa, mahasiswa, guru dan dosen bukan sekadar ikrar biasa. Ikrarnya melibatkan nasionalisme dengan makna yang luas. Siswa, mahasiswa, guru dan dosen masa kini lebih kompleks masalah dan tuntutan yang dihadapi. Satu di antaranya, maraknya kosa kata asing yang menyusup dan menjejal dalam ejaan dan komunikasi sehari-hari dalam derap kehidupan masyarakat.
Belum lagi, makin merebak bahasa sosialita dalam jejaring media sosial. Istilah “alay” dalam kamus remaja masa kini makin dan terus meningkat. Kondisi ini, tanpa disadari, mampu membentuk “siswa, mahasiswa, guru dan dosen Alay” yang rapuh. Tidak siap menghadapi ketidakpastian dan perubahan. Sarjana milineal yang mudah terombang ambing.
Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di ruang publik makin digerus tanpa disadari banyak kalangan. Kondisi tersebut masih memperbincangkan fenomena penggunaan bahasa Indonesia sebagai media komunikasi. Apabila bahasa Indonesia dalam kepentingan teks dan kalimat dalam bentuk buku, ditemukan fakta yang lebih menarik. Fakta teks dan kalimat memiliki implikasi dalam tradisi membaca masyarakat.
Dengan menggunakan perbandingan jumlah buku yang diwajibkan dibaca siswa SMA di 13 negara, termasuk Indonesia. Tergambar bahwa di Amerika Serikat, jumlah buku yang wajib dibaca sebanyak 32 judul buku. Belanda 30 judul buku. Prancis sebanyak 30 judul buku. Jepang sejumlah 22 judul buku. Swiss sebesar 15 judul buku. Kanada sebanyak 13 judul buku. Rusia sejumlah 12 judul buku. Brunei yaitu 7 judul buku. Singapura adalah 6 judul buku. Thailand sebanyak 5 judul buku.
Sedangkan, Indonesia sebesar 0,8 judul buku. Angka itu menggambarkan rata-rata nol koma, tidak sampai satu judul buku! Padahal Toko buku di Indonesia sebanyak 2.802 buah dalam kurun waktu 17 tahun.
Modal Pengetahuan adalah budaya. Modal itu sebagai dasar bagi pengambilan keputusan, terkait dengan ekonomi maka menjadi dasar untuk melakukan transaksi. Kapital pengetahuan seperti halnya kapital budaya membentuk kelas sosial, artinya tidak setiap orang dapat memahami sebuah peristiwa (event) ataupun produk (goods) budaya.
Mereka mengapresiasi peristiwa dan produk budaya sesuai dengan tingkat edukasi, pekerjaan, penghasilan, dan kebiasaan (Richard, 1996). Karena itu, modal budaya adalah bersifat akumulatif dan tersedimentasi dari generasi ke generasi.
Tradisi membaca yang rendah karena dipicu jumlah buku dan bacaan yang dibaca rendah berimplikasi serius pada kemampuan menulis pun akan menjadi rendah. Bacaan rendah. Daya tulis rendah. Seolah ironi yang tidak pernah diperhatikan serius.
Kondisi yang terjadi, diungkapkan secara gamblang oleh Fernando Baez, dalam bukunya yang bertajuk Penghancuran Buku, dari masa ke masa,seolah menjadi pintu reflektif dalam memaknai lahirnya siswa, mahasiswa, guru dan dosen kali ini.
Idealisme adalah sumber perubahan. Perubahan terjadi karena tidak adanya kepuasan terhadap kondisi terkini, perubahan terjadi karena ada “kesalahan” atas suatu hal, perubahan dapat dilakukan hanya bila ada keberanian, dan keberanian untuk melakukan perubahan merupakan implementasi nyata dari idealisme.
Idealisme tumbuh secara perlahan dalam jiwa seseorang, dan termanifestasikan dalam bentuk perilaku, sikap, ide ataupun cara berpikir. Pengaruh idealisme tidak hanya terbatas pada tingkat individu.
Teringat pesan dari Raja Tanpa Mahkota, julukan popular seorang HOS Tjokroaminoto. ‘’Bila para siswa, mahasiswa, guru dan dosen ingin menjadi pemimpin besar maka menulislah seperti wartawan dan berbicaralah seperti orator.’’ Para siswa, mahasiswa, guru dan dosen boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah.(*)