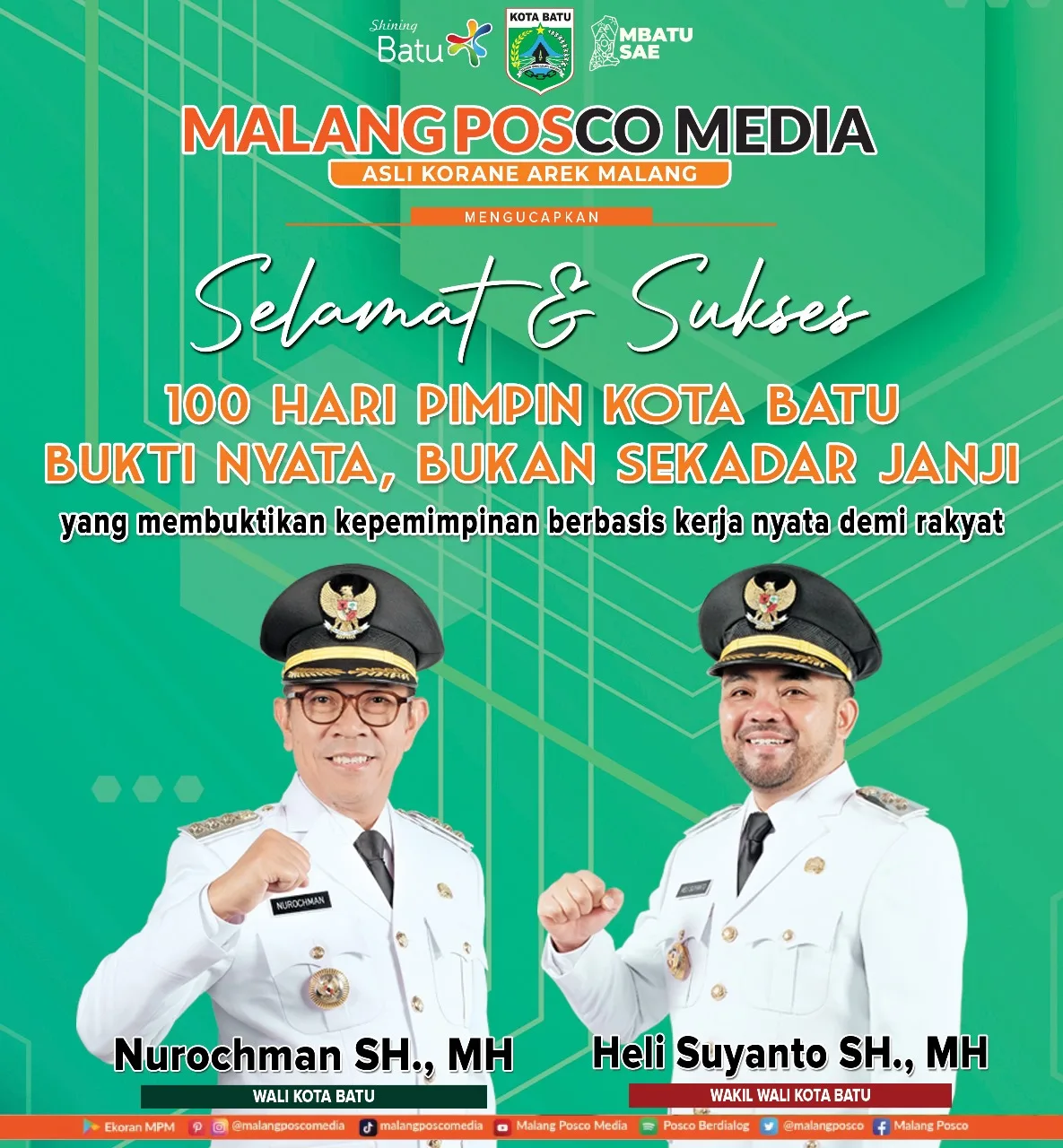Lebaran di Indonesia bukan sekadar perayaan keagamaan, tapi juga momen besar konsumsi. Dari tradisi belanja baju baru, hampers untuk keluarga dan kolega, sampai ritual tahunan mudik ke kampung halaman, semuanya membutuhkan biaya tidak sedikit. Belum lagi kewajiban berbagi dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR) yang meski menyenangkan, tetap menguras dompet, terutama bagi mereka yang sudah berstatus kepala keluarga atau punya banyak keponakan. Alhasil, euforia Lebaran sering kali diikuti realita pahit: saldo rekening menyusut drastis, dan rutinitas keuangan terganggu.
Fenomena ini bukan asumsi semata. Bank Indonesia memprediksi bahwa pada periode Ramadan dan Idul fitri, perputaran uang tunai meningkat hingga lebih dari Rp 180 triliun, naik lebih dari 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 160 triliun. Transaksi digital pun mencatat lonjakan, terutama melalui QRIS dan e-wallet, yang menunjukkan bahwa konsumsi tinggi tak hanya dilakukan secara konvensional, tapi juga digital. Singkatnya, Lebaran mendorong lonjakan pengeluaran lintas sektor.
Contoh nyata bisa dilihat dari meningkatnya penjualan merek-merek fesyen lokal seperti Erigo, Buttonscarves, atau Heaven Lights yang kerap laris manis menjelang Lebaran karena menawarkan busana muslim kekinian. Di ranah kecantikan, penjualan lipstik, parfum, hingga skincare meningkat signifikan menjelang hari raya.
Fenomena ini selaras dengan konsep lipstick effect, yaitu kondisi di mana masyarakat tetap berbelanja produk kecil dan terjangkau seperti lipstik atau barang fesyen sederhana sebagai bentuk pelarian psikologis di tengah tekanan ekonomi. Dalam konteks Lebaran, meski anggaran terbatas, masyarakat tetap ingin terlihat “pantas” saat berkumpul, dan memilih belanja yang mampu meningkatkan kepercayaan diri meski berdampak kecil secara ekonomi.
Dari sudut pandang manajemen keuangan, fenomena ini sangat dekat dengan konsep seasonal budgeting dan impulse spending. Saat momen tertentu seperti Lebaran, individu cenderung mengabaikan rencana anggaran demi memenuhi kebutuhan sosial dan emosional. Padahal, teori financial resilience menekankan pentingnya menjaga daya tahan keuangan dalam menghadapi fluktuasi pendapatan dan pengeluaran musiman.
Selain itu, teori mental accounting dari Richard Thaler menjelaskan bahwa manusia cenderung mengklasifikasikan uang ke dalam “kantong mental” yang berbeda. THR, misalnya, sering dipersepsikan sebagai “uang bonus” yang sah untuk dibelanjakan seluruhnya, bukan dikelola secara strategis.
Lalu, bagaimana cara kita mengembalikan kestabilan keuangan setelah pengeluaran Lebaran? Misi “balik modal” bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana namun disiplin. Pertama, lakukan evaluasi pengeluaran pasca-Lebaran. Cek kembali catatan transaksi, atau minimal histori e-wallet dan rekening bank. Dari situ kita bisa mengetahui seberapa besar “kerusakan” yang terjadi.
Kedua, buat rencana pemulihan keuangan dalam tiga tahap: jangka pendek (1 bulan), menengah (3 bulan), dan jangka panjang. Fokus awal bisa pada menyeimbangkan kembali pos pengeluaran rutin dan menyusun ulang prioritas belanja. Ketiga, aktifkan kembali kebiasaan menabung, meski nominalnya kecil. Prinsip snowball saving—menabung dari jumlah kecil yang konsisten terbukti efektif membangun ulang tabungan.
Keempat, hindari jebakan balas dendam keuangan, seperti langsung liburan atau belanja online lagi karena merasa “sudah hemat” saat mudik. Terakhir, gunakan momentum ini untuk membuat catatan keuangan pribadi yang lebih realistis, khususnya menjelang momen musiman berikutnya.
Momen setahun sekali lebaran memang kerapkali dijadikan pengecualian untuk berhemat. Namun, jika kebiasaan belanja besar tanpa perencanaan ini terus terjadi dari tahun ke tahun, dampaknya bisa merusak stabilitas finansial jangka panjang. Tak sedikit orang yang akhirnya menutup pengeluaran Lebaran dengan berutang, entah lewat kartu kredit, paylater, atau pinjaman online.
Di sinilah letak bahaya laten dari pola konsumsi musiman: ia terasa wajar karena hanya “setahun sekali,” namun akumulasinya bisa menimbulkan debt trap atau jebakan utang. Apalagi jika kebiasaan itu tidak diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan.
Masyarakat perlu mulai memandang momen-momen seperti Lebaran bukan hanya sebagai ajang merayakan kemenangan, tapi juga kesempatan membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat. Menjadi bijak bukan berarti anti-konsumsi, tetapi tahu kapan, bagaimana, dan untuk apa uang digunakan.
Lebaran memang momen penuh sukacita, silaturahmi, dan berbagi. Namun, jangan sampai euforia sesaat membuat kondisi dompet berdarah-darah di hari-hari berikutnya. Mengelola keuangan bukan soal pelit atau menahan diri, melainkan tentang menjaga ritme kebahagiaan agar tak putus di tengah jalan.
Kini saatnya kita berbenah, memulihkan dompet dengan strategi cerdas dan semangat baru agar perjalanan finansial pasca-Lebaran tetap ringan. Ingat, Lebaran boleh selesai, tapi hidup terus berjalan. Maka, mari pastikan setiap rupiah kembali bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Dompet sehat, hati pun lebih tenang.(*)