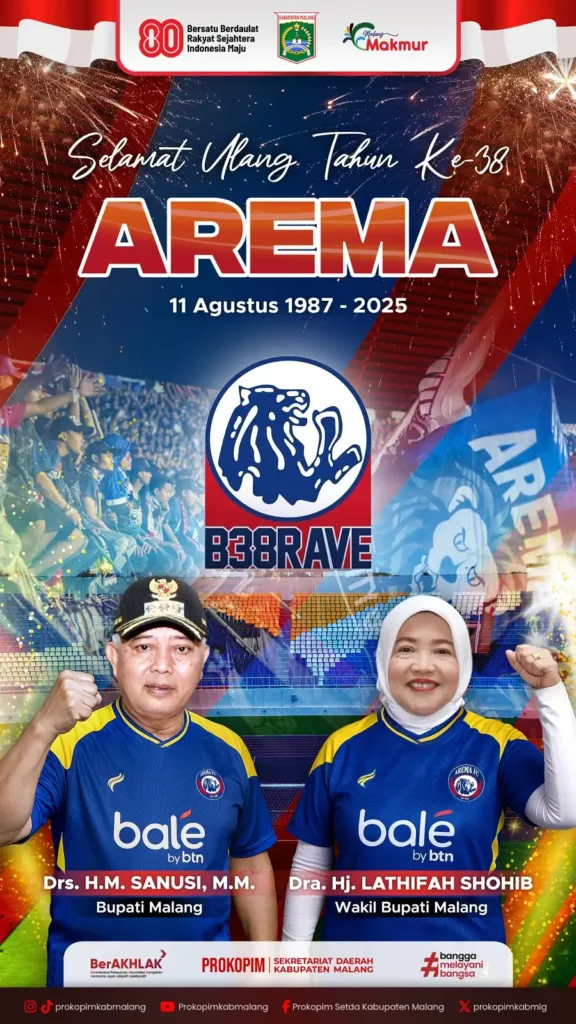Beberapa waktu lalu, penulis menyempatkan diri mengunjungi sebuah toko buku yang “dulu” sangat populer di kota Malang. Letaknya strategis, dekat dengan sebuah pusat perbelanjaan, tempatnya di pinggir jalan. Halamannya luas, parkir nyaman dan ruang baca yang menyenangkan, yang dulu tak pernah sepi pengunjung.
Saat masuk ke pintu toko itu, kita akan disambut dengan berbagai macam judul buku. Aroma khas buku langsung menyambut perpaduan antara kertas baru dan tinta cetakan yang selalu memunculkan rasa nostalgia.
Namun alih-alih ramai seperti sebelumnya, toko buku itu tampak lengang. Hanya ada dua-sampai tiga orang pengunjung lain yang terlihat, dan bahkan mereka hanya berjalan-jalan tanpa membeli. Di balik meja kasir, seorang pegawai termenung sambil sesekali melihat ke arah pintu masuk, mungkin berharap ada pelanggan yang datang membeli buku.
Pemandangan itu membuat penulis sedih sekaligus merenung. Buku yang disimbolkan sebagai jendela ilmu, begitu kata pepatah lama yang masih relevan hingga kini. Tapi kenyataannya saat ini memperlihatkan bahwa jendela itu tampaknya mulai ditinggalkan. Di tengah dominasi media digital, keberadaan toko buku fisik makin terpinggirkan. Masyarakat kini lebih memilih menggulir layar ponsel ketimbang membalik halaman buku. Maka wajar jika toko buku kian sepi, bahkan sebagian gulung tikar.
Buku “Dulu” Simbol Peradaban
Sejarah mencatat bahwa buku memiliki peran penting dalam peradaban manusia. Sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15, buku menjadi alat utama penyebaran ilmu pengetahuan. Toko buku pun menjamur, menjadi ruang interaksi antara manusia dan ilmu.
Di Indonesia, toko buku seperti Gunung Agung, Gramedia, dan Toga Mas pernah menjadi ikon budaya literasi, tempat orang berburu ilmu, inspirasi, dan sekaligus hiburan. Namun kini, toko buku tidak lagi menjadi tempat yang ramai dikunjungi.
Banyak orang lebih memilih mengakses pengetahuan melalui media digital, seperti e-book, artikel daring atau bahkan video pembelajaran yang dirasa lebih mudah dijangkau. Meski tidak sepenuhnya menggantikan buku fisik, media online telah mengubah cara kita membaca dan belajar anak-anak kita.
Dari sini kita menyadari bahwa kemunculan media internet membawa kemudahan luar biasa dalam mengakses informasi. Seseorang dapat membaca ribuan artikel, jurnal, bahkan novel hanya lewat gawai di genggamannya. Tak hanya itu, muncul pula platform-platform seperti Google Books, Scribd, Wattpad, hingga aplikasi baca digital lokal seperti Ipusnas dan Gramedia Digital yang memungkinkan pengguna membaca secara instan tanpa harus ke toko buku.
Di satu sisi, perkembangan ini merupakan kemajuan teknologi yang perlu diapresiasi. Literasi menjadi lebih inklusif dan murah. Namun di sisi lain, ia menjadi ancaman nyata bagi toko buku fisik. Pola konsumsi literatur masyarakat telah berubah. Buku bukan lagi menjadi prioritas utama, terlebih dalam bentuk cetakan.
Data dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) menunjukkan bahwa penjualan buku fisik menurun rata-rata 20–30 persen setiap tahunnya sejak pandemi COVID-19. Meskipun pandemi telah berlalu, tren pembelian buku digital tetap bertahan. Beberapa toko buku besar bahkan terpaksa menutup cabangnya.
Gunung Agung, salah satu jaringan toko buku tertua di Indonesia, secara resmi menghentikan operasionalnya pada tahun 2023 setelah 70 tahun beroperasi. Yang menyedihkan bukan hanya toko buku yang tutup, tapi nilai dan filosofi yang turut menghilang bersamanya. Toko buku bukan sekadar tempat transaksi jual beli, tetapi ruang budaya yang mempertemukan gagasan, mendekatkan orang pada ilmu, dan menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini.
Dahulu, kita sering melihat anak-anak duduk lesehan di toko buku, membaca majalah anak atau komik edukatif. Beberapa remaja memilih buku-buku motivasi atau fiksi remaja. Orang tua pun mencari buku parenting atau religi. Interaksi seperti itu memberi ruang tumbuhnya kebiasaan membaca secara alami.
Kini, momen itu jarang ditemukan. Ketika toko buku sepi, maka ruang publik yang mendidik perlahan menghilang tergerus oleh arus.
Haruskah Pasrah pada Digital
Pertanyaannya kini, apakah toko buku akan benar-benar hilang dengan perkembangan terknologi? Atau masih adakah harapan untuk bangkit? Jawabannya bergantung pada sejauh mana toko buku mampu bertransformasi dan sejauh mana masyarakat menyadari pentingnya mempertahankan budaya literasi berbasis fisik.
Di beberapa negara, toko buku independen justru kembali hidup dengan pendekatan baru. Misalnya di Jepang dan Korea Selatan, toko buku kecil berkembang karena mereka menawarkan pengalaman membaca yang lebih personal dan estetis.
Di Eropa, toko buku digabungkan dengan kafe, ruang diskusi, atau galeri seni—menciptakan ekosistem literasi yang hidup dengan menggabungkan konsep toko buku dan ruang komunitas. Toko buku perlu menjadi lebih dari sekadar ruang jual beli. Ia bisa menjadi ruang pertemuan, tempat diskusi, kelas menulis, atau klub membaca. Hal ini dapat menciptakan loyalitas dan keterikatan emosional dengan pengunjung.
Tak bisa dimungkiri, untuk menyelamatkan keadaan toko sehingga tidak punah dibutuhkan peran aktif kita semua, untuk menyadarkan kembali bahwa membaca adalah jendela dunia yang tidak boleh ditinggalkan. Masyarakat pun perlu menyadari bahwa membeli buku fisik adalah bagian dari investasi jangka panjang bagi kualitas berpikir bangsa. Memilih membaca buku cetakan, meski lebih mahal atau tidak instan, adalah bentuk perlawanan terhadap budaya instan yang kian meluas.(*)