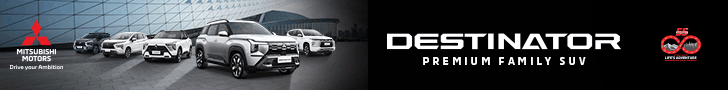Setiap bulan Oktober, bangsa Indonesia memperingati dua momentum penting yaitu Hari Sumpah Pemuda, juga Bulan Bahasa dan Sastra. Sejarah mencatat, pada 1928, pemuda menjadi sosok penting dalam perubahan. Saat itu pemuda dari berbagai daerah berkumpul di Jakarta dan bersepakat mengikrarkan tiga janji: bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.
Keputusan itu bukan main-main. Kita dapat membayangkan, ada ratusan suku dengan bahasa daerah masing-masing rela melepas ego demi satu bahasa yang menyatukan. Momentum Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa ini mengingatkan kita, bahwa menjaga kesantunan berbahasa tidak hanya penting untuk menghormati sejarah 1928, tetapi juga bagian dari gerakan kebahasaan nasional hari ini.
Bulan Bahasa seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai ajang lomba karya tulis, baca puisi, atau pidato, tetapi juga kesempatan untuk merefleksikan bagaimana bahasa digunakan dalam kehidupan nyata. Apakah pemuda mampu menjaga martabat bahasa Indonesia di tengah derasnya arus gaul digital? Pertanyaan ini yang menjadi inti dari perayaan Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa.
Fenomena Bahasa Gaul dan Tantangannya
Kini, hampir satu abad berlalu, bahasa Indonesia memang sudah menjadi milik semua, tetapi ada fenomena menarik sekaligus memprihatinkan. Anak muda memunculkan fenomena berbahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul dalam interaksi sehari-hari, yang mengesankan keakraban dan kreativitas, namun kadang cenderung kasar. Media sosial penuh dengan kata-kata singkatan, plesetan, bahkan umpatan yang kadang dianggap “biasa” saja. Pertanyaannya, apakah ini bagian dari perkembangan bahasa yang wajar, atau justru tantangan baru dari semangat Sumpah Pemuda?.
Tidak dapat dipungkiri, bahasa gaul adalah warna khas remaja. Dari generasi 90-an yang akrab dengan istilah cuy dan bokap-nyokap, hingga generasi TikTok dengan “anjay”, “gaskeun”, atau “receh”, semua menunjukkan bagaimana anak muda selalu punya cara untuk tampil beda. Bahasa gaul menjadi simbol solidaritas sekaligus identitas.
Di sisi lain, tren sekarang, kata-kata kasar, ejekan, bahkan umpatan menjadi bumbu sehari-hari. Tidak hanya di tongkrongan, tapi juga di kelas, komentar medsos, hingga konten video. Banyak remaja merasa itu bukan masalah, “Ah, kan cuma bercanda.” Sedangkan, normalisasi bahasa kasar dapat menurunkan standar kesopanan, melemahkan rasa hormat, dan mengikis makna bahasa sebagai perekat.
Penelitian menunjukkan bahwa bahasa gaul memang menjadi ekspresi kreatif anak muda, terutama dalam bentuk akronim, singkatan, dan plesetan yang populer di media sosial (Wulandari, 2021; Nurgiansah, 2021). Lain cerita jika kreativitas ini justru bercampur dengan kata-kata kasar, sehingga membentuk budaya permisif terhadap kekerasan verbal.
Dalam studi ilmiah yang dilakukan oleh Stapleton (2022) menegaskan bahwa umpatan memiliki efek emosional yang signifikan, sedangkan studi eksperimental terbaru juga menemukan bahwa paparan kata-kata kasar dapat meningkatkan emosi negatif serta memengaruhi cara orang lain menilai pembicara (IJIP, 2024). Jadi, kalau bahasa gaul dibiarkan tanpa kontrol, yang lahir bukan lagi solidaritas, melainkan ketegangan sosial.
Refleksi Sumpah Pemuda di Era Digital
Kalau kita kembali ke 1928, para pemuda menyadari bahwa bahasa adalah jembatan persatuan. Mereka memilih bahasa Indonesia, yang kala itu belum populer karena ingin membangun identitas pemersatu bangsa yang merangkul semua suku. Kalau waktu itu mereka bersikeras dengan bahasa daerah masing-masing, mungkin persatuan Indonesia sulit terwujud.
Hari ini, tantangannya berbeda. Bahasa Indonesia memang sudah dominan, tapi kesantunannya kian terancam oleh budaya “asal keren” atau “asal viral.” Remaja lebih nyaman mengekspresikan diri lewat kata-kata ekstrem, karena dianggap lucu atau lebih “relate.” Padahal, bahasa adalah juga cermin sebuah bangsa.
Refleksi Sumpah Pemuda seharusnya tidak berhenti pada seremoni, tapi menjadi pengingat bahwa bahasa yang diwariskan oleh para pendahulu harus dijaga. Menjaga berarti memelihara nilai persatuan sekaligus kesantunan.
Lalu, apakah remaja harus berhenti berbahasa gaul? Tidak juga. Justru bahasa gaul menunjukkan kreativitas luar biasa. Kata-kata baru dapat muncul hanya dari satu video viral dan langsung diadopsi jutaan orang. Hal itu menjadi bukti betapa pergaulan generasi muda penuh dinamika. Yang perlu dilakukan adalah membedakan antara gaul yang kreatif dengan gaul yang kasar atau sarkasme.
Kreatif berarti menciptakan istilah unik tanpa merendahkan orang lain. Kasar berarti membudayakan ejekan, umpatan, atau istilah yang melemahkan martabat. Kita perlu menyadari bahwa menjadi gaul tidak harus meninggalkan sopan santun. Justru dengan memadukan kreativitas bahasa dan kesantunan, remaja dapat menunjukkan kelas yang berbeda, keren sekaligus bermartabat.
Peran Pemuda Digital Menjaga Kesantunan
Sebagai generasi digital, pemuda punya peran strategis. Pertama, remaja dapat mulai menyadari akan kekuatan kata. Kata-kata dapat menyatukan, dapat pula memecah belah. Kedua, menggunakan media sosial untuk menyebarkan istilah yang positif, bukan sebaliknya memperkuat budaya umpatan.
Ketiga, menjadi teladan kecil di lingkungan sendiri, di kelas, di tongkrongan, di grup WhatsApp, di dinding komentar media sosial. Kalau dulu pemuda 1928 berjuang lewat ikrar, pemuda sekarang dapat berjuang lewat bahasa yang santun di dunia digital.
Pemuda masa kini boleh gaul, boleh kreatif, boleh berekspresi mengikuti tren, namun jangan sampai mengurangi nilai kesantunan bahasa kita. Mari belajar dari semangat pemuda era 1928, yang dapat menjadikan bahasa sebagai alat pemersatu, maka pemuda hari ini juga dapat menjadikan bahasa sebagai alat untuk menjaga martabat. Gaul memang keren, tetapi santun lebih berkelas.(*)