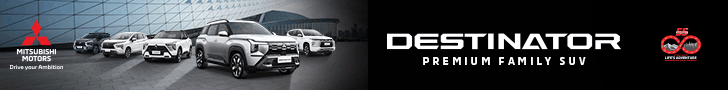Di tengah gempuran globalisasi yang semakin masif, krisis karakter anak-anak Indonesia menjadi tantangan besar yang tak bisa diabaikan. Mereka adalah digital natives, lahir dan besar bersama gawai, media sosial, serta berbagai konten global yang tanpa batas. Sayangnya, kemajuan ini tidak serta merta diiringi dengan kematangan karakter.
Fenomena seperti rendahnya empati, menurunnya rasa hormat terhadap orang tua dan guru, mudahnya anak terlibat dalam perundungan siber (cyber bullying), hingga kecenderungan merasa asing dengan budaya sendiri menjadi cerminan persoalan karakter anak masa kini.
Pendidikan kultural adalah proses pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai budaya lokal, seperti kearifan lokal, adat istiadat, etika sosial, dan tradisi yang telah lama mengakar dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, “Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kodrat itu.”
Nilai-nilai tersebut sesungguhnya telah menjadi panduan moral bagi masyarakat Nusantara jauh sebelum sistem pendidikan formal berkembang. Namun, arus modernisasi dan dominasi budaya luar yang masif melalui media sosial dan teknologi digital telah menggerus pemahaman anak-anak terhadap budayanya sendiri. Akibatnya, banyak anak yang kehilangan identitas kultural dan nilai-nilai luhur yang semestinya menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak.
Basis Penguatan Karakter
Pendidikan karakter seharusnya tidak hanya ditanamkan melalui ceramah atau aturan-aturan moral normatif, tetapi juga melalui keteladanan dan pembiasaan nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya lokal seperti sopan santun, toleransi, kerja sama, dan rasa hormat terhadap orang tua dan guru dapat menjadi landasan dalam pembentukan karakter anak.
Misalnya, dalam budaya Jawa dikenal falsafah “unggah-ungguh” yang mengajarkan etika sopan santun dalam bertutur dan bertindak. Dalam budaya Minangkabau terdapat prinsip “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” yang menekankan harmonisasi antara agama dan adat. Sedangkan di Bali, konsep “Tri Hita Karana” mengajarkan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam.
Menurut teori pendidikan Progressive Education dari John Dewey, pendidikan harus berakar pada pengalaman nyata dan lingkungan anak. Dewey percaya bahwa pendidikan yang kontekstual akan membentuk individu yang demokratis dan bertanggung jawab sosial. Artinya, pendidikan karakter tidak akan efektif jika dipisahkan dari budaya yang hidup di sekitar anak. Dewey menyatakan, “Education is not preparation for life; education is life it self.” Oleh karena itu, budaya bukan sekadar materi pelengkap, melainkan sumber kehidupan nilai dalam proses pendidikan itu sendiri.
Strategi Implementasi Pendidikan Kultural
Membangun karakter anak digital melalui strategi kultural bukan berarti menolak kemajuan teknologi, melainkan menjadikannya sebagai alat untuk memperkuat nilai-nilai budaya lokal. Ada beberapa strategi konkret yang dapat dilakukan.
Pertama, mengintegrasikan nilai budaya lokal dalam pembelajaran. Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi guru untuk menerapkan pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek. Di sinilah nilai-nilai budaya lokal dapat dijadikan materi penguatan karakter.
Misalnya, siswa diajak membuat vlog tentang tradisi lokal di daerah mereka, mengadaptasi cerita rakyat menjadi komik digital, atau membuat podcast tentang nilai-nilai adat di lingkungan mereka. Dengan pendekatan ini, anak tidak hanya mengenal budaya, tetapi juga menginternalisasi makna dan relevansi nilai tersebut dalam kehidupan modern.
Kedua, digitalisasi budaya lokal sebagai media pembelajaran. Anak-anak sangat akrab dengan platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Maka, penting bagi pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas untuk memproduksi konten digital edukatif yang mengenalkan budaya lokal secara menarik dan sesuai bahasa anak-anak zaman sekarang. Konten ini bisa berupa lagu tradisional yang dikemas modern, animasi cerita rakyat, atau tutorial permainan tradisional yang ditayangkan di media sosial.
Ketiga, pelibatan keluarga sebagai teladan budaya. Pendidikan karakter paling efektif tetap berasal dari lingkungan keluarga. Orang tua harus menjadi model dalam mempraktikkan nilai-nilai budaya, seperti berbicara sopan, menghargai perbedaan, dan menjalankan tradisi keluarga. Praktik sederhana seperti makan bersama sambil bercerita tentang asal-usul keluarga, mengenalkan bahasa daerah, atau mengajak anak mengikuti upacara adat dapat memperkuat identitas kultural anak.
Keempat, menciptakan ruang komunitas budaya yang ramah digital. Pemerintah dan masyarakat perlu mendorong lahirnya ruang-ruang komunitas—baik fisik maupun digital—yang memfasilitasi anak-anak untuk mengenal dan mencintai budaya. Misalnya, sanggar budaya yang membuat program live streaming kegiatan seni daerah, komunitas permainan tradisional online, atau forum diskusi virtual tentang kearifan lokal yang melibatkan generasi muda.
Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, pendidikan kultural tidak hanya menjadi romantisme masa lalu, tetapi bisa hadir sebagai kekuatan yang adaptif dan strategis untuk menjawab persoalan karakter anak zaman digital. Anak-anak tidak harus memilih antara menjadi modern atau tradisional, tetapi justru bisa tumbuh sebagai pribadi yang cakap teknologi sekaligus berakar pada nilai-nilai budaya luhur.
Gerakan Back to Culture bukan sekadar slogan, melainkan panggilan untuk kembali ke akar—ke nilai-nilai kultural yang telah terbukti menjadi penuntun moral dalam masyarakat Indonesia. Dalam membentuk karakter anak digital, kita tidak bisa hanya mengandalkan teknologi, tetapi perlu strategi yang menyentuh sisi identitas dan kebijaksanaan lokal. Karena sesungguhnya, budaya bukan beban masa lalu, melainkan cahaya untuk masa depan.(*)