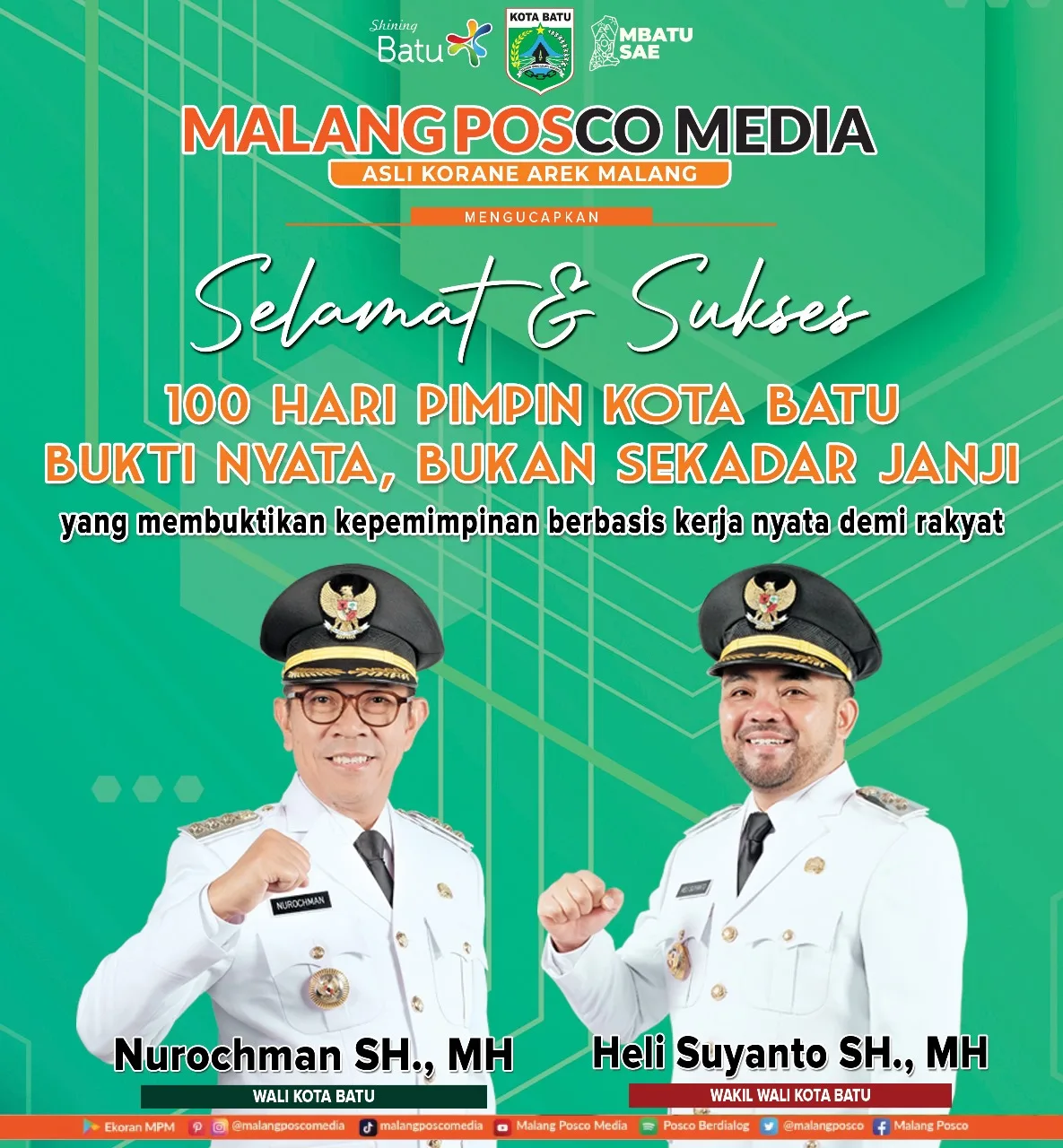Semakin hari, dunia pendidikan dihadapkan pada pembelajaran yang semakin menantang. Hal ini bukan saja karena perkembangan zaman dan dinamika kurikulum nasional, namun juga karena sisi sosial masyarakat pasca hempasan Covid-19. Secara khusus kita juga dihadapkan pada karakter pemelajar yang merupakan kategori milenial.
Pemelajar milenial memiliki karakter yang berbeda dibandingkan pada masa orang tua atau generasi kakek/ neneknya belajar. Beberapa karakteristik generasi milenial yang cukup menonjol adalah menyukai cara yang interaktif dan kolaboratif dalam belajar. Mereka lebih memilih hubungan yang casualdengan gurunya (Sophia Sanchez, 2016).
Menyadari kondisi ini, tentu perlu perubahan pola pikir dan budaya dalam proses pembelajaran. Termasuk di dalamnya, bentuk relasi guru dan peserta didik, tentu dengan tidak mengabaikan norma-norma kesantunan yang harus tetap dipegang teguh sesuai budaya bangsa kita.
Bagaimana memenuhi kebutuhan milenial ini? Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah melalui teknik coaching. Mengacu pada definisi coaching sesuai standar ICF (International Coach Federation), coaching adalah “Hubungan kemitraan antara coach dan individu yang dijalin melalui proses kreatif untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional dirinya.”
Dengan teknik coaching akan tercipta percakapan dua arah antara coach dan coachee dalam rangka memberdayakan potensi coachee. Dalam relasi ini, peran pendidik adalah sebagai coach dan peserta didik sebagai coachee.
Bagaimana coaching bisa menjadi teknik alternatif yang memberi solusi pada strategi pembelajaran bagi milenial? Hal ini terkait dengan pola kerja dalam coaching. Interaksi dalam coaching adalah percakapan dua arah. Di sini, pendidik dan peserta didik akan membangun relasi yang baik dan membuat komitmen dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan.
Maka, peserta didik tidak menjadi objek yang hanya sekadar didikte. Peserta didik justru dilatih untuk mendesain tujuan, menggali potensinya serta segala kemungkinan kolaborasi untuk mencapai tujuannya. Melalui teknik ini, peserta didik secara bertahap akan memaknai belajar sebagai sebuah kebutuhan untuk mencapai tujuan yang ia tetapkan, bukan sebagai keterpaksaan.
Pada saat yang sama, ia juga akan belajar, bahwa ekosistem di sekitarnya adalah potensi yang bisa memberikan dukungan bagi dirinya. Ia pun akan belajar menghargai setiap hal dan setiap orang sebagai bagian penting dalam proses bertumbuh dirinya.
Menelaah pola coaching tersebut, dapat dilihat bahwa yang sedang dibangun bukan melulu tentang keberhasilan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan kompetensi diri, namun juga karakter serta sikap sosial. Dalam proses percakapan coaching, baik secara individu maupun kelompok kecil, peserta didik akan membiasakan diri berpikir kritis dan kreatif melalui stimulasi pertanyaan dari pendidik selaku coach. Sesudahnya, peserta didik memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan apa yang sudah menjadi komitmennya. Dalam merealisasikan tujuannya, akan ada proses komunikasi, kreativitas, dan kolaborasi.
Mengacu pada proses coaching tersaji di atas, teknik coaching bukan hanya memenuhi kebutuhan model pembelajaran yang sesuai dengan karakter milenial. Proses dan tindak lanjut dari coaching juga memberikan latihan keterampilan abad 21 (Prima Sari, 2017) untuk transformasi pendidikan (Etistika Yuni Wijaya; Dwi Agus Sudjimat; Amat Nyoto, 2016).
Keterampilan abad-21 yang disebut sebagai 4C meliputi Critical Thinking and Problem Solving, Creativity, Communication Skills, danAbility to Work Collaboratively. Proses coaching yang menjadi budaya dalam interaksi pendidik dan peserta didik, pada akhirnya akan membantu perubahan growth mindset baik dalam diri pendidik maupun peserta didik.
Teknik coaching menjadi alternatif pembelajaran yang lebih memfasilitasi karakter dan strategi pembelajaran bagi milenial, sekaligus sejalan dengan misi Kemendikbudristek dalam Merdeka Belajar. Menyadari hal ini, memberdayakan pendidik dengan keterampilan coaching menjadi hal yang penting.
Ada beberapa cara untuk membekali pendidik dengan keterampilan coaching. Seperti belajar mandiri dalam Platform Merdeka Mengajar, mengikuti Program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak, bekerja sama dengan komunitas coaching, hingga memanfaatkan jasa coaching profesional. Tentu pilihan tersebut disesuaikan dengan urgensi dan tingkat kompleksitas dukungan yang dibutuhkan oleh sekolah dalam membangun budaya coaching di ekosistem pendidikannya.
Selain fokus pada menumbuhkembangkan ekosistem pembelajaran yang lebih kondusif bagi peserta didik, teknik coaching dapat pula dimanfaatkan bagi unsur-unsur pendukung pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Seperti misalnya dalam hal supervisi, organisasi/ kepemimpinan, pengembangan SDM, dan lainnya.
Bisa dibayangkan potensi besar yang dapat ditumbuhkan dalam sebuah ekosistem pendidikan yang menjalankan teknik ini secara menyeluruh dan konsisten. Budaya dan pola pikir bertumbuh akan semakin cepat terbangun serta menciptakan branding khas pada ekosistem tersebut.
Sebagai ilustrasi penutup, beberapa sesi coaching yang pernah dipraktikkan penulis, telah berhasil membuat siswa bermasalah dalam bahasa Inggris menjadi juara Speech Contest, dan sekelompok siswa pemalu berhasil menjadi EO (Event Organizer) sekaligus narasumber inspiratif dalam beberapa webinar pelajar.
Mengutip ungkapan dari Albert Einstein, “Insanity is doing the same thing over and over, and expecting different results,” kita dihadapkan pada sebuah tantangan. Jangan mengharapkan hal yang biasa dan berulang untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda, apalagi luar biasa. Coaching adalah salah satu teknik yang dapat menjadi peluang luar biasa itu. Dengan membangun kesadaran sepenuhnya dari peserta didik, peluang sukses dari setiap peserta didik semakin terbuka lebar. Dari sana pula salah satu amanah pendidik akan menemukan jalannya.(*)