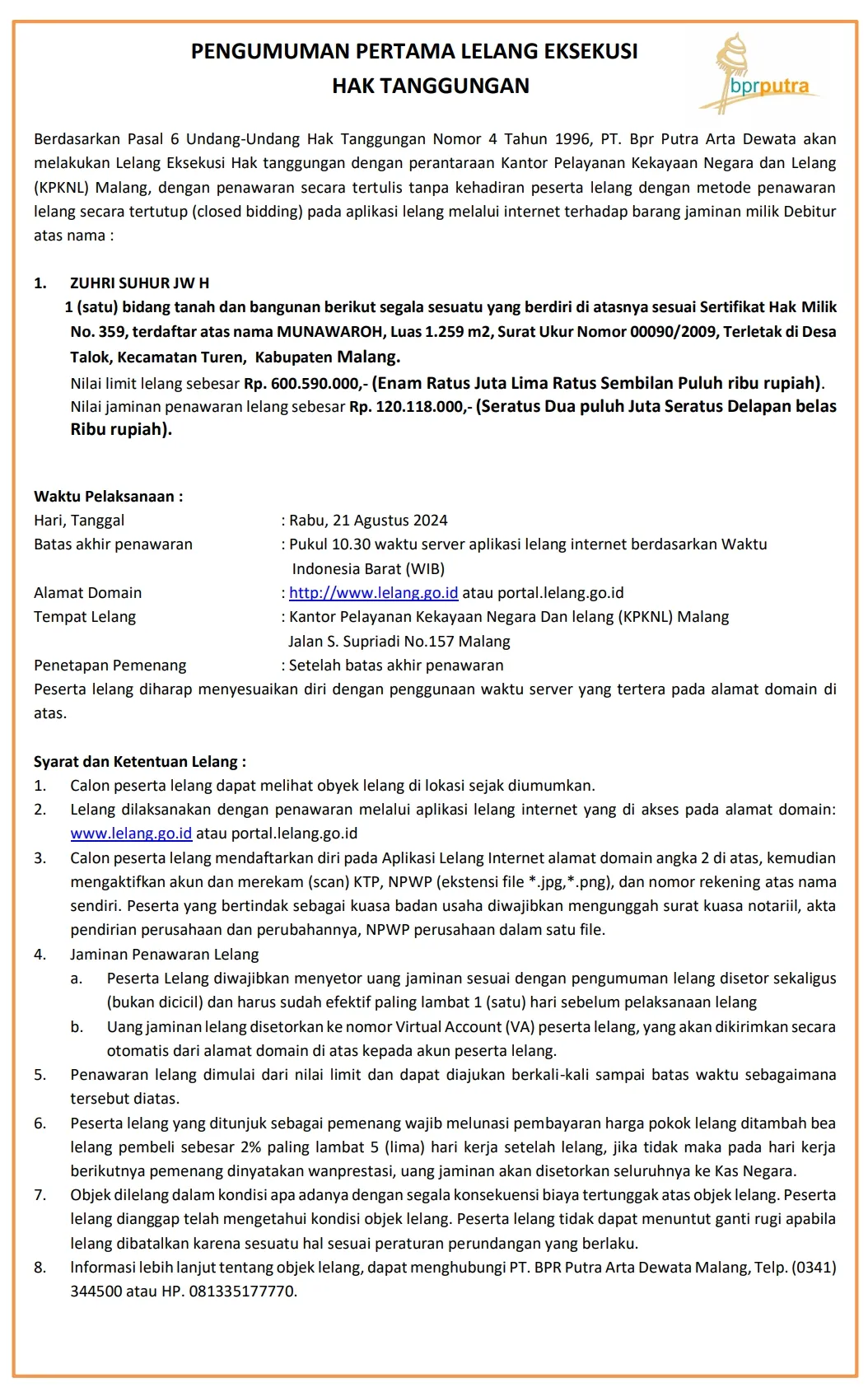MALANG POSCO MEDIA – Farel Prayoga, penyanyi cilik asal Banyuwangi sukses menggoyang Istana Merdeka. Tamu kehormatan, para menteri, dan beberapa jenderal yang mengikuti upacara 17 Agustus turun dari tribun kehormatan ikut berjoget bersama Farel yang menyanyikan lagu ‘’Ojo Dibandingke.’’
Jenderal Dudung terlihat asyik bergoyang, Sri Mulyani pun ikut turun menggoyang-goyangkan badan. Prabowo Subianto–yang biasanya serius–ikut turun ke bawah dan berjoget bersama hadirin lainnya. Presiden Jokowi berdiri tersenyum senang di podium kehormatan, sementara Ibu Negara Iriana Joko Widodo bergoyang-goyang dari tempat duduknya.
Suasana upacara yang biasanya serius dan tegang menjadi cair. Semua yang hadir ikut terhanyut dalam suasana. Bahkan, Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo–yang sedang puyeng memikirkan kasus Ferdy Sambo—juga ikut bergoyang pelan-pelan dari tempat berdirinya di podium.
Ketika Farel selesai menyanyikan lagu pertama, ada permintaan dari audiens supaya menambah satu lagu lagi. Jokowi yang ditawari lagu apa yang ingin didengar spontan menjawab ‘’Joko Tingkir.’’ Rupanya Jokowi tahu lagu itu sedang viral dan banyak digemari publik.
Farel bersiap menyanyikan ‘’Joko Tingkir.’’ Tapi tim lapangan yang mengelilingi Farel terlihat saling berbisik-bisik, dan kemudian lagu itu batal dinyanyikan. Sebagai gantinya Farel mengulangi lagi lagu ‘’Ojo Dibandingke.’’
Kalau saja Farel jadi menyanyikan Joko Tingkir suasana akan makin meriah dan reaksi netizen akan makin heboh. Rupanya tim Istana khawatir lagu itu akan memicu kontroversi dan reaksi pro kontra kalau dinyanyikan di depan Jokowi. Musababnya, beberapa kalangan mengecam lagu Joko Tingkir karena dianggap melecehkan ulama.
Penampilan Farel menjadi simbol desakralisasi terhadap Istana yang dilakukan oleh Jokowi. Selama ini Jokowi mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari rakyat jelata, wong cilik, dan Istana bukan tempat yang sakral seperti pada era Presiden Soeharto.
Di masa kepemimpinan Presiden Soeharto di era Orde Baru Istana adalah locus kekuasaan yang sakral. Soeharto menempatkan dirinya sebagai penguasa Jawa yang mendapatkan kekuasaan dari pulung yang turun dalam bentuk wahyu kedaton. Wahyu ini sakral dan hanya turun kepada orang-orang pinilih, orang-orang yang terpilih.
Dalam konsep kekuasaan Max Weber seseorang menjadi pemimpin karena mendapatkan mandat rakyat melalui pemilihan, atau menjadi pemimpin karena kharismanya diakui oleh rakyat. Seseorang juga bisa menjadi pemimpin karena mengklaim mendapatkan wahyu kedaton dari dewa-dewa. Model kekuasaan inilah yang diterapkan di sistem mornarki atau kerajaan.
Sebagai penganut kejawen tulen Pak Harto meyakini kekuasaannya merupakan wahyu. Karena itu ia memperlakukan kekuasaannya sebagai sesuatu yang sakral. Semua atribut kekuasaan kepresidenan juga menjadi objek sakralisasi. Kekuasaan adalah sakral dan Istana adalah sakral.
Tidak sembarang orang bisa memasuki Istana, dan ketika seseorang diizinkan masuk ke Istana dia tidak boleh bertindak sembarangan. Bernyanyi dan berjoget di Istana tidak akan diizinkan oleh Soeharto karena bertentangan dengan sifat Istana yang sakral.
Kondisi itu berubah total setelah Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi presiden. Gus Dur melakukan dekonstruksi terhadap kekuasaan dan terhadap Istana. Sebagai aktivis demokrasi yang berlatar belakang kiai, Gus Dur langsung melakukan desakralisasi dengan membongkar tatanan birokratis yang ditinggalkan oleh Pak Harto.
Gus Dur dengan santai menerima tamu dengan bersandal dan mengenakan sarung. Tetamu istana juga bebas keluar masuk dengan pakaian informal seadanya. Para kiai yang sering menjadi tamu Gus Dur bisa datang ke istana dengan bersarung dan bersandal seperti sang tuan rumah.
Hal ini dilakukan oleh Gus Dur sebagai bentuk perlawanan kultural dengan melakukan dekonstruksi terhadap kekuasaan Soeharto yang elitis-transenden. Gus Dur menjadikan kekuasaan merakyat dan profane. Puncak dari dekonstruksi kekuasaan yang dilakukan Gus Dur ditunjukkan ketika Gus Dur keluar dari Istana setelah pemakzulan oleh DPR. Ketika itu Gus Dur tampil memberi pernyataan pers dengan mengenakan piyama dan celana pendek. Gus Dur kemudian meninggalkan istana dengan pakaian itu.
Meskipun tidak didasari oleh filosofi yang sama, Jokowi juga melakukan dekonstruksi dan desakralisasi kekuasaan Istana. Sepuluh tahun masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) suasana Istana kembali seperti era Soeharto. SBY ialah seorang demokrat, tetapi ia mempunyai disiplin militer yang tinggi dan sangat hati-hati menjaga citra sebagai pemimpin. SBY berbicara dan bertingkah laku secara ‘’orchestrated’’, dengan sangat rapi dan teliti. Segala atribut kekuasaan, termasuk Istana, kembali menjadi sakral.
Sepeninggalan SBY Jokowi menampilkan wajah kekuasaan yang lebih merakyat, setidaknya pada tampilan fisiknya. Jokowi secara ‘’orchestrated’’ menampilkan citra sebagai bagian dari wong cilik yang sederhana.
Meski demikian, tampilan fisik itu tidak serta- merta mewakili esensi. Penulis Australia, Ben Bland, menyebut Jokowi sebagai ‘’Man of Contradiction’’, manusia yang penuh kontradiksi dengan dirinya sendiri. Bland melihat Jokowi mengalami banyak kontradiksi antara citra dan kenyataan.
Momen 17 Agustusan bersama Farel Prayoga adalah momen desakralisasi Istana oleh Jokowi. Kekuasaan yang sekarang dipegang oleh Jokowi dan Istana yang ditempatinya didapat dari mandat rakyat, dan karena itu harus dikembalikan kepada rakyat ketika mandat itu berakhir.
Itu artinya, Jokowi harus rela mengakhiri jabatannya pada 2024, dan tidak melakukan rekayasa apa pun untuk memperpanjang periode, atau sibuk kasak-kusuk mempersiapkan pengganti.(*)